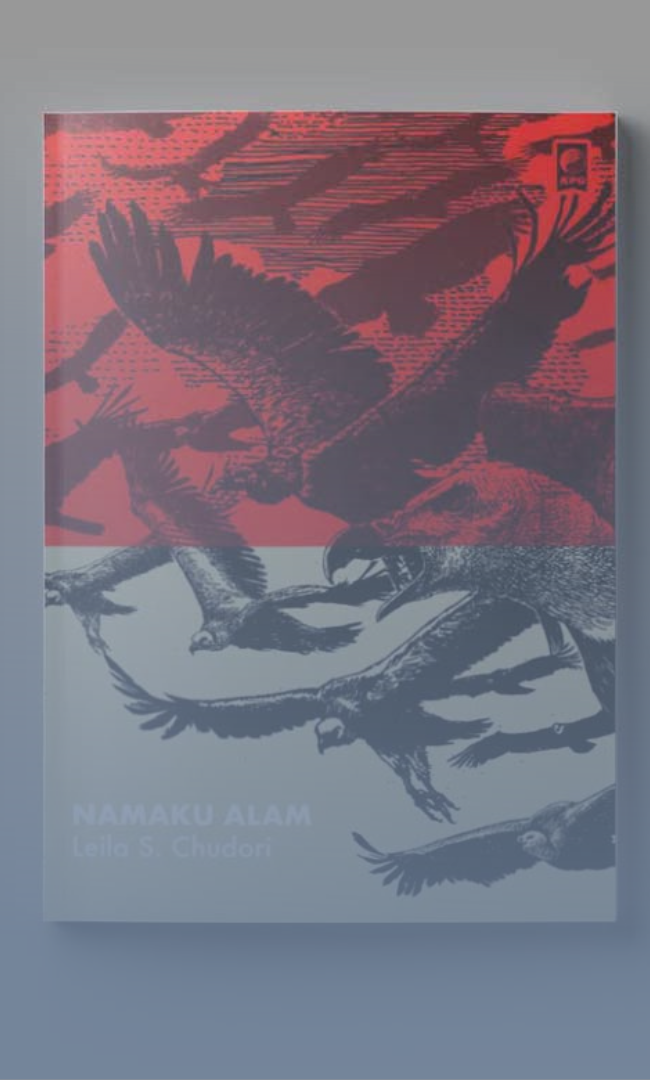Menerka Keabadian Puisi Irfan Ilmy
Katanya, hidup harus ulet. Namun, hidup yang ulet ternyata bisa menemui hasil akhir berbeda. Pepatah sunda bilang, “cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi dekok”. Sekecil apapun usaha, lambat laun berbuah hasil. Yopi Setia Umbara, dalam sajaknya menggambarkan hasil keuletan dalam bentuk lain, “kutulis namamu berulangkali di air”.
Sifat ulet adalah hal yang pertama kali berkesan bagi saya tentang sosok Irfan Ilmy dan pergulatannya dengan puisi. Ia seperti tak pernah absen dalam forum-forum sastra di kampus, atau bahkan menyelenggarakan sebuah forum kecil untuk beberapa pegiat sastra. Karyanya pun tersebar di berbagai media cetak dan daring.
Suatu malam, dia sengaja datang ke kamar kontrakan saya hanya untuk berbincang soal puisi. Kemudian di malam itu, kami menulis puisi berantai. Hasil puisi itu beberapa tahun kemudian dapat ditemukan dalam antologi puisi karangan Irfan Ilmy yang diberi judul Abadi di Telapak Kaki (Bening Pustaka, 2019). Sebagai hadiah, saya ingin menerka, akankah sajak-sajak Irfan Ilmy abadi seperti judul bukunya?
Kehilangan Momen Puitik
Marilah kita mulai dari beberapa hal yang gagal. Keuletan dibangun atas repetisi aktivitas demi mencapai hasil maksimal. Sayangnya, repetisi itu justru bisa menjadi kegagalan jika tidak menghasilkan bentuk baru. Tak sengaja, saat saya membaca buku Irfan secara acak, saya menemukan kegagalan itu. Repetisi diksi dan makna dalam dua larik berikut:
“Subuh seperti pembatas buku dalam bacaan kehidupan/ yang lega/ fungsinya mengingatkan dan hadir menandai setiap mili/ waktu” (Subuh, hlm. 4)
“Percapakapan adalah pembatas buku/ menjadi pengingat atas halaman-halaman kenangan/ percakapan juga sekaligus pustakawan/ setia tunaikan kewajiban” (Percakapan di Perpustakaan, hlm. 67)
Irfan secara sadar atau tidak menggunakan diksi yang sama untuk metafor yang sama, yaitu batas buku sebagai bentuk pengingat atas kenangan-kenangan. Penyair, dalam kondisi tersebut, seperti tidak menemukan momen puitiknya. Dua sajak dengan dua kondisi berbeda, diungkap dengan cara yang sama.
Padahal, jika kita memikirkan medan makna, waktu subuh dan pembatas buku seperti hal yang berjarak. Saya membuka kembali sajak “Subuh” itu, siapa tahu memang suasana sajaknya adalah penyair yang sedang membaca buku di waktu subuh. Namun ternyata tidak, kalimat di atas adalah larik pembuka dalam sajaknya.
Irfan seolah gagal dalam menemukan momen puitik di subuh hari, dan hanya mengolah kata-kata nu penting jadi. Beda, misal, lirik lagu Letto yang masih saya suka sampai sekarang. “Ingatkah engkau kepada/ embun pagi bersahaja/ yang menemanimu/ sebelum cahaya”. Meski sederhana, sihir larik itu mendapatkan momen puitik waktu subuh yang khusyuk dan intim.
Banjir Karya yang Tergesa
Ternyata, keuletan Irfan juga bisa jadi sebuah kerja yang tergesa-gesa. Ia ulet, tetapi mungkin kurang sabar dalam menulis puisi. Ia hanya mengangkap dan menulis kata-kata, bukan menuliskan makna.
Coba kita lihat dalam sajaknya yang berjudul “Terminal” (hlm. 40): “Warung nasi diisi orang-orang dengan perut keroncongan/ Sementara wc umum diburu orang yang kebelet buang hajat/ masjid didatangi sedikit umat/ saat terdengar azan panggilan salat”. Tanpa Irfan menulis puisi, kebanyakan orang pasti akan tahu deskripsi tersebut ya memang wajar terjadi di terminal. Adakah yang impresi yang ingin Irfan tekankan soal terminal kepada pembaca? Saya rasa tidak.
Masalah lain dalam puisi Irfan ialah premis yang sebenarnya bisa saja salah, seperti dalam larik ini: “sajadah lebih sukar dijumpai/ daripada gedung-gedung mewah dan tempat hiburan” (Pulang). Kalimat “gedung-gedung mewah dan tempat hiburan” menjadikan “sajadah” tetap berada pada makna sebenarnya, yaitu sebagai alas salat, bukan sebagai metafora. Jika demikian, boleh diragukan, sesulit itukan kita menemukan sejadah?
Atau, Irfan memang merenung saat menulis puisi, tapi renungan yang biasa-biasa saja. Siapapun bisa berpikir demikian, bedanya, Irfan menuliskannya dalam bentuk puisi. Misalnya dalam sajak “Membayangkan Diri Jadi Mereka” (hlm. 55).
“Aku jadi bisu, mulut berhenti berbusa melihat kenyataan/ manusia-manusia tidur di pinggir jalan/ di emperan toko dan di becak miliknya sendiri/ suara dengkur mereka bercampur/ dengan deru knalpot motor dan beberapa mobil/ yang sudah uzur/ menahan kerubut gigil tubuh/ yang butuh sungguh”.
Selain renungan di permukaan, Irfan dalam sajak itu terlihat kurang terampil berbahasa. Memang mulut kita selalu berbusa dan berhenti ketika mendapati kenyataan yang mengejutkan? Kemudian, frasa “yang sudah uzur” dalam sajaknya itu merujuk ke tubuh atau knalpot motor dan beberapa mobil? Dan lain-lain, dan lain-lain.
Kekacauannya dalam memilih kalimat juga ditemui dalam beberapa sajak lainnya. Misalkan dalam beberapa kutipan larik-larik berikut. “hatiku mati bersama rutinitas yang menggenggam bebas” (Suara yang Dilupakan, hlm. 5); “ilmu yang berloncatan dari brankas pengetahuannya/ adalah mutiara-mutiara berharga” (Kiai, hlm. 8); “kabut mengembus lembut pada media malam yang pekat” (Kabut Berebut Tempat di Hatimu, 110). Kata-kata “rutinitas”, “brankas pengetahuan”, “media malam yang pekat” terasa ganjil.
Atau, rima yang dipaksakan yang membuat kenyamanan pembaca dalam mendalami makna justru terabaikan. Misalnya dalam larik berikut: “Aku akan punah/ maka aku harus berbenah/ aku akan hilang/ pada yang baik aku harus garang” (Aku Akan Hilang, hlm. 36). Kata “garang” dipaksakan. Kok pada yang baik harus garang? Apakah artinya pada yang jahat patut lembut?
Irfan dan Pertanyaan
Keuletan tak mungkin sepenuhnya sia-sia. Ada pula sajak-sajak Irfan Ilmy yang sangat menarik. Sajak paling saya suka ialah sajak berjudul “Cikondang” (hlm. 12), sama seperti Rendy Jean Satria dalam pengantar di buku Irfan ini. “Kukira di sinilah kita harus dibenamkan/ bersama tanah tempat tumbuh/ bersama udara-udara yang selalu kita hirup/ mulai saban subuh/ bersama ingatan-ingatan masa kanak yang menolak lumpuh/ kukira di sinilah kita harus melabuhkan tubuh”.
Namun, melihat gejala ketidaknyamanan saat membaca puisi Irfan, saya melihat potensi hadir ketika Irfan lebih banyak mempertanyakan realitas. Saat ia tidak terlalu pandai menyublimkan peristiwa, di mana sebenarya itu inti kerja puitik yang saya pahami, Irfan mampu segar saat bertanya. Seperti dalam puisinya berikut:
Mempertanyakan Banyak Hal
angin punya desir, pantai punya pasir
dan kau, punya
segalanya
aku seorang fakir yang hanya terus menerus berpikir
mengotakatik kebenaran yang selalu kusangsikan
selalu kupertayakan tentang
benar dan tidaknya
seperti apakah kau benar-benar mencintaiku
kekasih?
Bandung, 2017
Atau pertanyaan yang asyik dalam larik berikut: “kemana kau hendak memanduku kekasih?/ jalan-jalan sudah seperti semak yang dipenuhi/ tanaman dengan tajam duri di kanan kiri” (Yang Berhasil Masuk ke Dalam Mimpiku, 117).
Jadi, jika buku puisi ini adalah pertanyaan Irfan pada pembacanya, “Bagaimana puisi yang saya tulis dalam buku pertama ini?”, maka saya jawab, “rajin-rajinlah bertanya sebanyak mungkin, untuk baru memulai menulis”. Sebenarnya, ia sudah menyadari itu dalam puisinya sendiri, tinggal lebih rajin melakukannya. Jangan lebih banyak menulis puisi dengan sedikit pertanyaan liar dan tajam. “puisiku menyimpan pesan-pesan/ di tiap lapis makna kulepas benih pertanyaan”, tulis Irfan dalam sajaknya berjudul “Pertanyaan” (hlm. 88).
Sebagai penutup, saya menemukan gejala mengapa Irfan yang ulet itu justru seperti asal-asalan dan tergesa dalam menulis puisi adalah karena kredo kepenyairannya sendiri.
“Di sini pada pagi di kota/ Seorang penyair memainkan seruling di kepalanya/ Kata-kata menjadi raja kobra/ menari-nari menikmati alunan nada” (Seorang Penyair, hlm. 79)
“Tiada yang lebih puitis bagi seorang sarjana pengangguran/ selain menanti puisinya dapat dibaca seluruh semesta/ lewat surat-surat kabar/ saat-saat itu debar jadi debur yang hancur bila nyatanya/ puisi yang ia haarapkan tidak hadir di hari libur itu” (Tiada yang Lebih Puitis, hlm. 19)
Kredo yang lucu, bukan?[]
Keterangan Buku
Judul: Abadi di Telapak Kaki
Pengarang: Muhammad Irfan Ilmy
Penerbit: Bening Pustaka, Yogyakarta
ISBN: 978-623-7104-02-5
Tebal: xxii+127 hlm; 13 cm x 18 cm
Cetakan: Pertama, Januari 2019