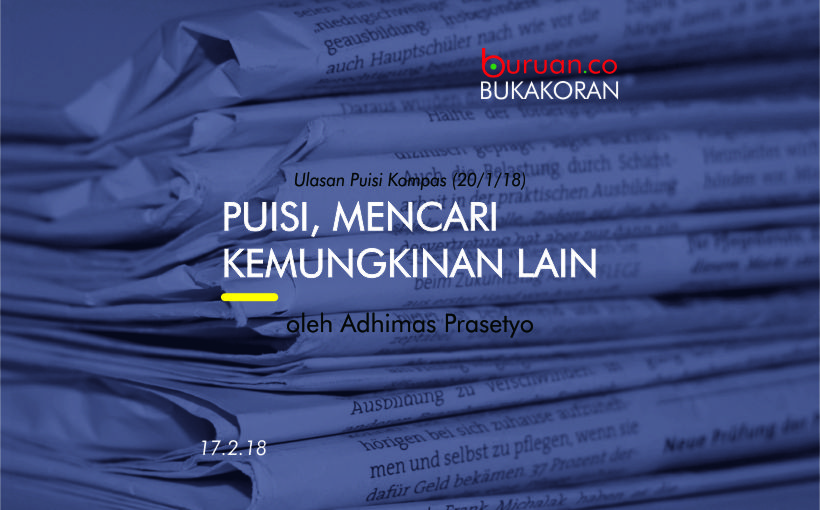
Puisi, Mencari Kemungkinan Lain
Preambul
Sebuah sajak ditulis mewakili objek dari perasaan puitis penyair. Saat mengolah perasaan puitisnya, penyair mempertimbangkan kemungkinan dari medium bahasa hingga dirasa tepat untuk mewakili perasaannya. Hingga akhirnya sebuah sajak dapat dinikmati oleh pembaca. Hal tersebut kurang lebih merupakan pemaparan dari trikotomi semiotik Charles Sanders Pierce, yaitu hubungan antara objek, representamen, dan interpretan.1
Dalam hal ini, objek merupakan sesuatu yang ada dalam benak penyair, baik berdasarkan hal konkret atau abstrak. Objek tersebut dituangkan dalam sajak yang berperan sebagai representamen—atau yang mewakili sesuatu. Lalu tanda-tanda dari sajak hadir dalam benak pembaca sebagai interpretan. Hubungan antara representamen dan interpretan dijembatani oleh ground, yaitu sebuah pengetahuan yang sama antara pengirim dan penerima tanda. Tentu dalam sebuah sajak, seringkali ground dengan sengaja dibuat menjadi bias, hingga antara penyair dan pembaca dapat menginterpretasikan sebuah sajak dengan cara yang berbeda.
Saat saya membaca sajak-sajak yang dimuat di Kompas pada akhir pekan ketiga Januari,2 saya melihat dua penyairnya, Aji Ramadhan dan Inggit Putria Marga, berusaha menghadirkan representamen dengan cara yang berbeda dalam menyampaikan maksudnya. Saya tertarik untuk membaca sajak-sajak tersebut dari kacamata semiotik, terutama interpretan yang hadir dalam benak saya sebagai pembaca.
Sajak sebagai Representamen
Tiga sajak Aji Ramadhan merupakan sajak yang hanya menghadirkan sebuah peristiwa, umumnya hadir berdasarkan citra visual. Representamen dari objek yang Aji gunakan umumnya bersifat konkret, sebut saja dalam sajak “Melempar Matahari Merekah” terdapat diksi matahari, bulan, embun, daun, tanah, semut, dan lain-lain. Aji tidak menghadirkan perasaan aku lirik atau pemaknaan yang bersifat aforisme dalam sajaknya. Maka saat saya membaca sajak ini, saya hanya diajak melihat proses malam menjadi pagi dan apa saja yang terjadi saat proses itu berlangsung.
Dalam sajak “Melempar Matahari Merekah”, diksi yang digunakan cenderung bersifat denotatif. Aku lirik berupaya menginterpretasikan gerak benda dengan cara memersonifikasikannya, misalnya bulan bergegas ke kantung waktu atau Di batas langit dan bumi, pagi/melempar matahari merekah. Hanya saja, personifikasi ini terkesan hanya mengabsen gerak benda-benda, bukan mewakili perasaan penyair.
Aji berusaha menyampaikan objek pagi hari dengan bait Matahari merekah dan/bulan bergegas ke kantung waktu. Pemilihan ini pada akhirnya dikarenakan sebab tertentu, Aji menulis objek proses terjadinya pagi dengan penggambaran matahari muncul dan mulai memanjang (merekah), sementara bulan bersembunyi dan tak terlihat (bergegas ke kantung waktu). Idiom kantung waktu merupakan metafora yang cukup segar meski abstrak, maka interpretan dapat melenceng dari objek yang dimaksud penyair.
Interpretan menjadi terganggu dengan representamen lain, misal pada larik Punggung para semut yang pegal/habis berpatroli/ perlu asupan vitamin K/milik matahari merekah atau pada larik Sepasang mawar beradu argumen/tentang cara terbaik/bersatu dengan matahari merekah. Ground yang dimiliki pembaca belum tentu sama dengan yang dimaksud penyair, apakah semut membutuhkan vitamin K? Apakah mawar memang beradu argumen? Tidak ada interpretasi makna yang lebih dari larik-larik ini, selain mewartakan apa yang terjadi. Semut dan mawar menjadi bersifat denotatif karena tidak ada isotopi yang membangun untuk memiliki makna lain. Pada akhirnya diksi yang bersifat konotatif juga mengemban beban denotatifnya, maka kelogisan penting untuk dibangun.
Sajak lain dari Aji Ramadhan kurang lebih memiliki gaya yang sama, yaitu mencoba menghadirkan representamen yang berisi peristiwa personal aku lirik. Sajak berjudul “Rugi” menceritakan peristiwa yang dialami kita saat mendaki gunung. Sedangkan sajak “Datang” bercerita tentang peristiwa aku lirik pada pagi hari.
Berbeda dengan dua sajak lain, saya menikmati sajak “Datang” karena dalam representamennya menghadirkan pengalaman pagi yang juga saya alami. Selain itu, sajak ini menghadirkan aforisme seperti Seorang anak enggan lagi tidur/karena pagi datang/menghiasi dinding hari harunya.
*
Sajak “Festival Purnama” karya Inggit Putria Marga menghadirkan peristiwa yang terjadi saat malam dengan bulan purnama di bulan November. Inggit menyampaikan objek malam dengan larik setelah kelopak matahari mengatup/dari balik bukit berpohon sedikit/kepala purnama menyembul. Diksi mengatup tepat digunakan karena matahari diibaratkan seperti bunga yang memiliki kelopak. Selain itu, sajak ini menghadirkan peristiwa-peristiwa kelam saat malam bulan purnama seperti di bawah berikut.
…
ke yang halus dan yang kasar, cahaya menyebar:
ke tangan istri yang sedang mencengkram leher kekasih suami
ke tangan ibu yang gemetar menghapus keringat dingin di dahi bayi
…
Pada bait terakhir bulan purnama disandingkan dengan petani, namun purnama tidak mengharapkan mendapatkan hasil dari cahaya yang diberikannya kepada peristiwa kelam yang dialami orang-orang. selama kelopak matahari terkatup/purnama menebar cahaya/tak seperti petani/tak berharap menuai yang ditabur di bumi.
Sajak “Tawa Materiya” karya Inggit menghadirkan intertekstual sebagai ground kepada pembaca, Maitreya dalam ajaran Buddha adalah Bodhisattva Maitreya atau Buddha yang akan datang. Diceritakan Maiterya menyaksikan tingkah laku para pendoa di kuil. Tawa Maiterya yang semakin melebar dapat diartikan sebagai sebuah ironi terhadap pendoa di kuil. Ground dalam sajak ini akan sangat berbeda antara penulis dan pembaca jika kisah tentang Maiterya tidak diketahui oleh pembaca. Selain itu, peristiwa para pendoa yang hadir beragam, yaitu ada yang sedih dan bersenang-senang, namun dari penghadiran tersebut, interpretan menjadi beragam tergantung pengetahuan yang dimiliki pembaca.
Sajak terakhir yaitu “Pengasih Kedasih”, menghadirkan peristiwa simbolik dari tokoh aku lirik dengan kegiatan mematahkan sayap kedasih, agar ia tidak terbang dan menjauh dari aku lirik. telah hamba patahkan sepasang sayap kedasih, sebab telur-telur kesedihan/yang bertahun dieram ulu hati hamba, menetas usai teringat takdir sayap/adalah membuat kedasih melayang menuju hutannya sendiri,. Burung kedasih sendiri memiliki mitos yaitu sebagai pengabar kematian. Interpretan saya terhadap sajak ini adalah aku lirik mematahkan sayap kedasih untuk memastikan kematiannya, karena ia terlalu murung melihat kerabatnya yang telah lebih dulu mati.
***
Usaha dua penyair di atas adalah menghadirkan representamen dari objeknya dengan cara beragam. Aji Ramadhan cenderung menampilkan peristiwa personal aku lirik dan mencoba memaknai gerak benda dengan personifikasi, sedangkan dua sajak Inggit Putria Marga menghadirkan intertekstualitas sebagai ground yang membantu pembaca memaknainya.
Representamen yang hadir dalam sajak Aji Ramadhan seakan mencari cara baru menyampaikan sesuatu, khususnya pada sajak “Melempar Matahari Merekah”. Inggit menggunakan representamen yang lebih kompleks yaitu memainkan intertekstual dengan cara yang lain, yaitu Maitreya yang tertawa dan mematahkan sayap kedasih.
Puisi akhirnya mencari kemungkinan lain dalam menyampaikan objek. Hal tersebut lumrah terjadi dalam proses penciptaan sajak. Acep Zamzam Noor pernah menyinggung hal ini, yaitu bahwa nilai puisi tidak semata-mata terletak pada apa yang diungkapkan, tapi lebih pada bagaimana cara mengungkapkan.3 Meskipun akhirnya harus ada pertimbangan lebih cermat terhadap representamen sebagai bentuk yang benar-benar mewakili objek.
2018
1 Disarikan dari Semiotik dan Penerapannya dalam Karya Sastra (Okke K. S. Zaimar, 2008: halaman 4).
2 Dapat dilihat di harian Kompas edisi 20 Januari 2018.
3 Disarikan dari Puisi dan Bulu Kuduk (Acep Zamzam Noor, 2011: halaman 22).





