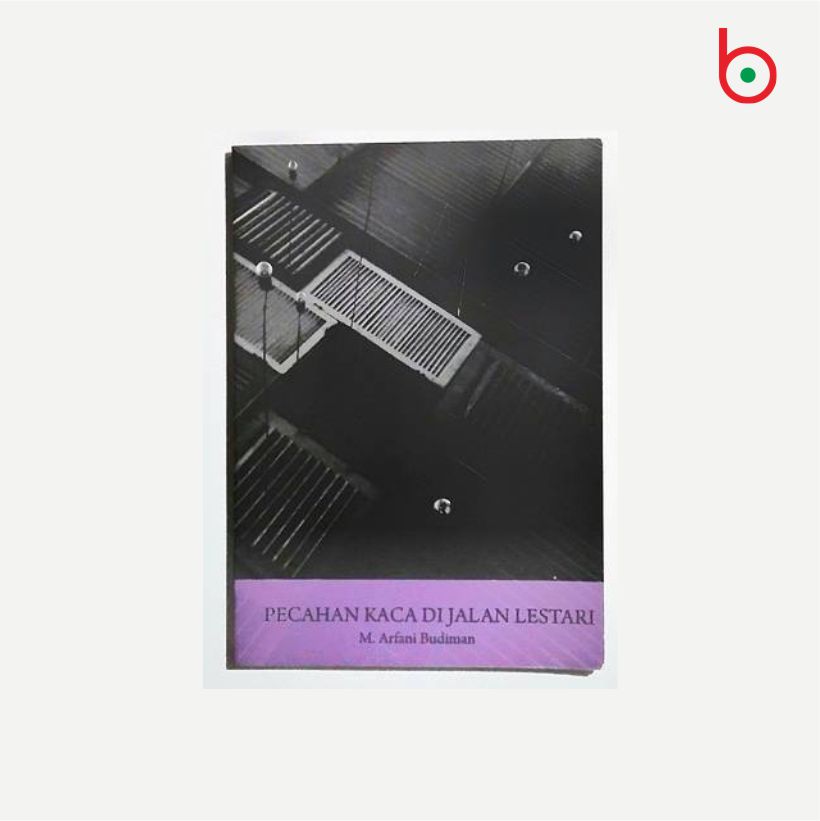
Tentang Sajak-Sajak yang Pecah
Preambul
Buku antologi puisi menjadi salah satu cara memberikan kesempatan kepada sajak untuk hidup di tengah masyarakat. Namun, dalam satu antologi puisi, kadang tidak semua sajak bisa diterima dan hidup di dalam benak pembacanya.
Ada banyak sebab yang bisa mengikat pembaca dengan sebuah sajak, baik dari teks dalam sajaknya sendiri atau kondisi pembaca saat menemukan sajak tersebut. Ikatan itu terjalin dalam satu keadaan yang barangkali bisa saya sebut mirip takdir.
Saya sendiri sebagai pembaca kadang tidak (sanggup) membaca habis satu antologi puisi untuk menikmatinya. Bagi saya, berempati kepada satu sajak adalah pekerjaan melelahkan. Apalagi saat membaca seluruh sajak dalam satu antologi puisi.
Saya butuh waktu tiap kali membaca sebuah sajak. Mungkin saya bisa memahami maksud dari sebuah sajak dalam sekali baca, tapi saya pikir jika hanya membacanya seperti itu, saya tidak selalu bisa mengenal diri saya yang diwakili oleh teks sajak itu.
Begitu juga saat membaca antologi puisi Pecahan Kaca di Jalan Lestari karya M. Arfani Budiman. Resensi ini saya tulis sebagai pengalaman saat membacanya.
Sajak-Sajak yang Pecah
Buku Pecahan Kaca di Jalan Lestari yang ditulis oleh M. Arfani Budiman terdiri dari tujuh puluh sajak. Sajak-sajaknya dibagi dalam tiga subjudul yaitu Pecahan, Kaca, dan Jalan Lestari.
Saya rasa sajak-sajak dalam buku cukup konsisten, artinya, penyair telah menemukan dan memiliki bentuk tertentu untuk menyuarakan gagasannya. Penyair seolah tidak lagi mengkesplorasi bentuk, tapi menawarkan isi dalam sajak-sajaknya.
Bentuk sajak-sajak dalam buku ini adalah sajak pendek dan padat. Satu sajak hanya terdiri dari satu bait. Meskipun begitu, sajak-sajaknya tetap kaya bermacam tawaran gagasan.
Hal yang bisa dilihat secara dominan adalah penggunaan idiom. Idiom ini dapat terlihat dari frasa yang digunakan sebagai judul sajak, misalnya “Mata Senja”, “Gerimis Luka”, “Samudera Waktu”, “Wajah Pagi”, “Lukisan Malam”, dan masih banyak lagi. Frasa-frasa dari judul-judul tersebut menghadirkan makna utuh yang dibentuk dalam kesatuannya.
Mari kita baca salah satu sajaknya yang bertakdir dengan saya,
Mata Senja
musim-musim mengacuhkanku
memapah takdir menuju tubir senja
luka begitu mesra membelai tangan pujangga
sementara keabadian kata-kata menjelma
percik api
membakar seluruh doa menjadi gugusan sunyi
Dalam sajak ini, alih-alih menghadirkan isotopi senja, sajak bernarasi tentang aku lirik yang merasa terasing di waktu senja, keterasingan sendiri tertulis dalam larik musim-musim mengacuhkanku. Sebab aku lirik bukanlah senja yang sedang bernarasi, karena dalam larik ke dua terdapat larik memapah takdir menuju tubir senja, maka aku lirik sendirilah yang mengalami senja, bukan sebagai senja.
Saya mengartikan mata senja sebagai hal-hal yang terjadi kepada aku lirik saat senja hari. Senja di sini masih saya artikan secara denotatif, tetapi jika saya dalami lagi makna konotatifnya misalnya makna senja yang dikaitkan dengan usia, maka mata senja adalah pandangan aku lirik selama hidupnya terhadap beberapa hal.
Aku lirik akhirnya terkesan tabah menerima segala hal yang dialami. Misalnya dalam larik luka begitu mesra membelai tangan pujangga, cara aku lirik menerima luka adalah penyandingannya dengan diksi mesra. Hingga di larik terakhir tertulis membakar seluruh doa menjadi gugusan sunyi. Bagi aku lirik, hal yang tersisa dari doa yang bisa dipahami sebagai permohonan atau harapan, hanyalah kesunyian.
Saya menganggap sajak M. Arfani Budiman adalah sajak yang pecah. Pecah dalam dua pengertian, pecah dalam bentuk dan gagasan sajak.
Bentuk dan Gagasan Sajak yang Pecah
Bagi saya, sajak adalah pembangunan sebuah peristiwa yang mengajak pembaca berempati kepada isi sajak tersebut. Sedangkan sajak-sajak M. Arfani Budiman di buku ini sangat kuat dalam membangun peristiwa yang dialami oleh aku lirik.
Saya anggap peristiwa yang dibangun dalam sajak-sajak M. Arfani Budiman adalah sesuatu yang pecah. Maksudnya, saya harus membacanya utuh, lalu menyusun kembali maksud sajak tersebut.
Maka dalam menikmati sajak-sajak M. Arfani Budiman, saya lebih dulu mencoba memahami apa yang dialami aku lirik. Menyusun peristiwa demi peristiwa, sebelum akhirnya berempati terhadap tawaran sudut pandangnya tentang berbagai hal.
Misalnya dalam sajak “Mata Senja” sebelumnya. Saya memahami aku lirik sebagai orang yang mengalami senja, baik senja dalam arti bagian dari hari atau senja dalam arti usia.
Sebab setelah membacanya secara utuh, saya tidak harus mencari keterkaitan makna idiomatis dari frasa mata senja dengan isi sajak lebih utuh. Bagi saya sajak ini bermain pada bangun peristiwa dan gagasan. Begitu juga pada sajak-sajak lain dalam buku ini.
Sedangkan gagasan dalam sajak-sajak di buku ini, hampir semua memandang sesuatu yang telah pecah. Pecah dalam artian dunia atau dirinya sendiri yang rusak atau tidak lagi utuh hingga membuat aku lirik terasing. Seperti penggambaran aku lirik saat pasrah menerima kenyataan di sekitarnya dalam sajak “Mata Senja”.
Barangkali ada hal yang tidak bisa langsung dipahami, baik dari tingkat kata, frasa, atau kalimat. Namun kita bisa memahami gagasan umum sajak-sajak tersebut. Beberapa gagasan penyair dalam sajak-sajak di buku ini sebenarnya menawarkan sesuatu yang besar dari hal-hal kecil yang dialami oleh aku lirik.
Saya tidak menghadirkan sajak lain, sebab saya percaya sajak akan menemukan pembacanya sendiri. Seperti yang saya tulis di awal, mungkin bisa dibilang takdir yang akan mempertemukan sajak dengan pembacanya.
Terakhir, saat saya membaca sesuatu yang pecah dalam sajak-sajak di buku ini, saya menyadari sesuatu memang telah pecah dalam diri saya sendiri. Jauh sebelum saya membaca sajak-sajak di buku ini.[]
Keterangan Buku
Judul: Pecahan Kaca di Jalan Lestari
Penulis: M. Arfani Budiman
Penerbit: ASASUPI
Cetakan: I, April 2017
ISBN: 978-602-6675-00-2





