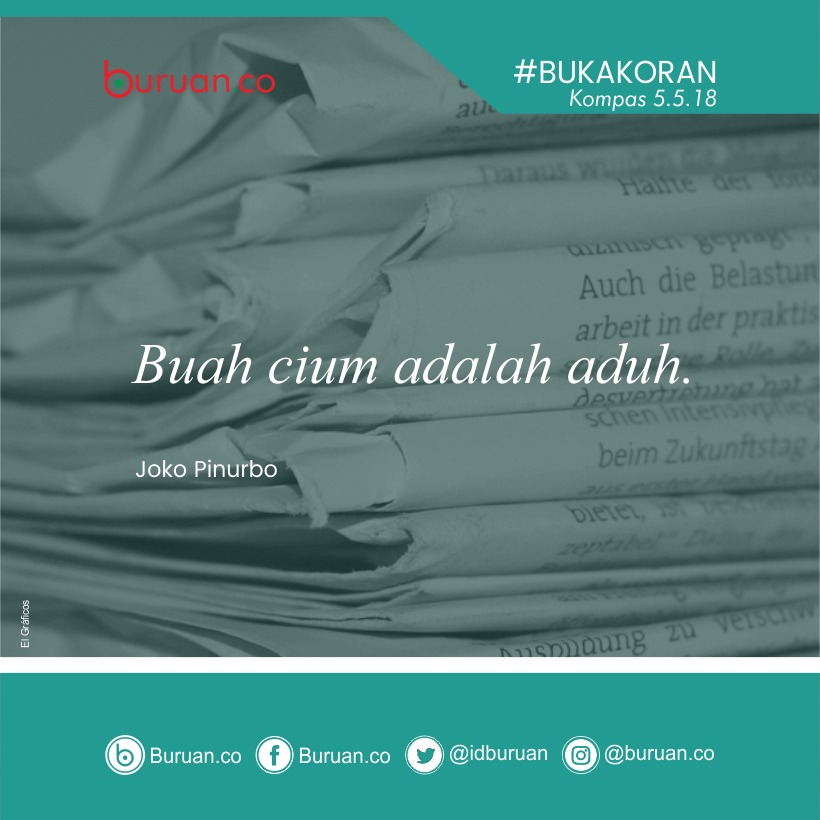
Memetik Buah Tangan Jokpin
Sabtu, 5 Mei 2018, 13 sajak Joko Pinurbo (Jokpin) terbit di harian Kompas. Hampir semua sajak Jokpin yang terbit menggunakan judul dari idiom atau ungkapan yang sudah sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Berikut adalah judul-judul sajak Jokpin tersebut: “Ninabobok”, “Putri Malu”, “Mimpi Basah”, “Cuci Mata”, “Datang Bulan”, “Kabar Burung”, “Kopi Tubruk”, “Masuk Angin”, “Buah Bibir”, “Kamar Kecil”, “Rumah Tangga”, “Buah Hati”, dan “Anak Buah”.
Pertanyaannya, apakah Jokpin melakukan pergeseran makna, penyimpangan makna, atau penciptaan makna baru atas idiom-idiom atau ungkapan-ungkapan yang menjadi judul sajaknya tersebut?
Pergeseran makna (displacing of meaning), penyimpangan makna (distorsing of meaning), dan penciptaan makna (creating of meaning) merupakan ciri ketidaklangsungan ekspresi puisi yang dimapankan oleh Michael Rifattere—kritikus asal Perancis—dalam Semiotics of Poetry yang banyak dirujuk akademisi sastra, terutama yang menaruh minat pada kajian semiotika.
Dari 13 sajak Jokpin, saya akan coba baca tiga buah sajaknya, yaitu: “Buah Bibir”, “Buah Hati”, dan “Anak Buah”. Saya mencoba memilih tiga sajak yang mengandung buah ini untuk diulas sebagai upaya untuk memetik buah tangan Jokpin.
Buah Bibir
Buah bibir adalah ciuman:
manis yang tak mau habis,
segar yang takut hambar,
hangat yang ingin lekat,
sesap yang menyisakan senyap,
utuh yang berangsur luruh.
Buah cium adalah aduh.
(Jokpin, 2017)
Ungkapan buah bibir yang selama ini kita mengerti memiliki makna sebagai bahan pembicaraan orang. Atau, bagi masyarakat pengguna media sosial tentu sangat kenal dengan istilah trending topic. Dalam karya Jokpin, buah bibir adalah ciuman, persis seperti larik pertama yang ditulis dalam sajaknya. Apakah itu sebuah makna baru dari buah bibir? Tentu saja belum tentu. Dengan sajak ini, Jokpin mengajak pembaca untuk menikmati sensasi buah bibir lewat keunggulan gaya bahasanya—yang dikenal jenaka.
Jokpin tidak serta-merta menyajikan makna dari sajak “Buah Bibir” ini. Akan tetapi, ia mengajak pembaca untuk larut dalam narasi pendek puitik nan kuat secara asonansi tentang buah bibir. Betapa tidak pendek, sajak ini hanya disusun dalam tujuh larik dan dua kalimat dalam satu bait saja. Namun, meski meski pendek, asonansi yang demikian rapat pada sajak ini akan menimbulkan bunyi yang panjang.
Coba saja simak larik-larik berikut ini dengan indera pendengaran kita: manis yang tak mau habis,/segar yang takut hambar,/hangat yang ingin lekat,/sesap yang menyisakan senyap,/utuh yang berangsur luruh. Dengan disiplin asonansi ketat seperti ini, sangat wajar jika pembaca akan mudah mengingat sajak yang disusun dengan cara seperti Jokpin lakukan ini.
Kejenakaan metafora buah bibir adalah ciuman yang disiratkan Jokpin, tentu memberikan kesegaran dari makna ungkapan buah bibir yang selama ini kita sepakati, sadar atau tidak sadar. Jika topik yang kita pahami selama ini abstrak, maka pada sajak Jokpin menjadi sesuatu “materi”. Bukankah ciuman merupakan suatu proses yang sangat materiel? Dimana ada interaksi antara pencium dan yang dicium (atau malah sama-sama saling mencium) yang meninggalkan kesan. Kesan-kesan atau impresi ciuman itu sendiri disiratkan Jokpin secara reflektif sebagai manis yang tak mau habis,/segar yang takut hambar,/hangat yang ingin lekat,/sesap yang menyisakan senyap,/utuh yang berangsur luruh.
Lantas, apakah buah bibir dalam sajak “Buah Bibir” ini bergeser, menyimpang, memiliki makna baru? Rasanya tidak. Akan tetapi, Jokpin memberikan ilustrasi bagaimana suatu topik beserta kesan-kesannya dengan penggambaran imajinatif menjadi sesuatu yang reflektif. Refleksi itu dapat kita baca di penutup larik sekaligus kalimat akhir sajaknya, Buah cium adalah aduh. Selain menciptakan ungkapan baru buah cium, di sini kita dapat memetik sebuah refleksi dari kata aduh yang disiratkan Jokpin. Bukankah secara harfiah ‘aduh’ merupakan kata seru untuk menyatakan rasa heran, sakit, dan sebagainya?
Buah Hati
Langit memberkati kita
dengan hujan
yang istikamah.
Hatimu bersemi kembali,
tambah sabar,
tumbuh subur
dan berbuah.
Kau di dalam selimut,
aku di dalam kau,
merekah di malam basah.
Ingin kupetik
buah hatimu
yang merah
dan kau berkata, “Lekaslah.”
(Jokpin, 2017)
Untuk memetik makna dari sajak Jokpin, kita terlebih dahulu harus menaruh tabik pada keunggulannya dalam bermain-main dengan bahasa. Jokpin seolah telah melepaskan diri dari isi (makna) sebuah sajak—yang sering jadi pertanyaan dalam lembar ujian di zaman sekolah (semoga hari ini sudah tidak ada pertanyaan seperti itu lagi). Jokpin seperti memberi contoh, bahwa bermain-main dengan bahasa sangat penting selain menimbang makna yang ingin disampaikan.
Seperti dalam sajak “Buah Hati” ini, Jokpin begitu enaknya menulis kata ‘istikamah’ dalam bait pembuka sajaknya, Langit memberkati kita/dengan hujan/yang istikamah. Penggunaan kata ‘istikamah’ ini sudah pasti Jokpin tidak main-main. Sebab, sangat mungkin kata itu memang sudah diperhitungkan harus ditulis dalam sajaknya. Apalagi jika kita perhatikan, setiap akhir bait dalam sajaknya berakhir dengan bunyi –ah: yang istikamah, dan berbuah, merekah di malam basah, dan kau berkata, “lekaslah.”
Selain itu juga, kata ‘istikamah’ memang berarti konsisten. Jadi, dalam konteks bait sajak ini, Jokpin sedang menuturkan hujan yang terus turun (mengguyur). Kalau ditulis seperti itu, tentu biasa saja kan? Tapi ketika ditulis dengan Langit memberkati kita/dengan hujan/yang istikamah, bait ini menjadi menarik, karena Jokpin menyajikan kreativitas dengan memaksimalkan salah satu bahan utama sajak, yaitu kosakata. Kata ‘istikamah’ itu tak akan menarik jika tak diikuti bunyi –ah di akhir bait-bait selanjutnya. Ia hanya akan jadi tempelan saja.
Di samping itu, Jokpin begitu pandai memanfaatkan psikologi massa, dimana penggunaan kata ‘istikamah’ ini demikian sering digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Jokpin seakan-akan merebut kata itu dari ketidaksadaran massa menjadi kata yang amat berdaya pada sajaknya.
Jika kita baca sekilas, sajak “Buah Hati” ini seperti adegan sebuah percintaan. Aku lirik dalam sajak ini menuturkan fragmen-fragmen percintaan pada sebuah malam dalam hujan. Coba kita cermati ulang bait ketiga dalam sajak ini: Kau di dalam selimut,/aku di dalam kau,/merekah di malam basah.
Pertanyaannya, apakah fragmen-fragmen tersebut menuju pada sebuah percintaan yang imanen? Tentu saja membuat kita penasaran.
Baca juga:
– Belantara Kata Ahmad Yulden Erwin
– Seandainya Puji Kuswati Membaca Fitra Yanti
Sajak “Buah Hati” yang ditulis dengan teknik dramatis seperti ini memang harus membikin penasaran. Apakah sajak ini mengisahkan percintaan manusiawi atau menuju pada suatu imanensi? Hal inilah yang menjadikan sajak Jokpin yang dituturkan oleh seorang tokoh, memiliki alur, dan diakhiri suspens, menjadi menarik.
Anak Buah
Anak buah
yang hijau muda
gemetar
dibelai anak angin
di tangkai tua.
Anak air
di bawah pohon
berdebar menunggu
anak daun
terlepas
dari anak cabang
dan kembali
menjadi anak bumi.
Aku mau
jadi anak susu
bagi buah kopi
yang meranum
di batang tubuhmu.
(Jokpin, 2018)
Membaca puisi Jokpin, memang seperti membaca prosa dalam puisi. Namun, karena ia disusun dari unsur-unsur puisi yang ketat, metafora yang segar, dan imaji yang luwes, membuat identitasnya tetap kukuh sebagai sebuah puisi. Ia tak terjebak pada sekadar cara bertutur yang naratif.
Metafora-metafora seperti: anak angin, anak air, anak daun, anak cabang, anak bumi, dan anak susu dalam sajak “Anak Buah” ini saya kira cukup segar. Metafora-metafora tersebut seolah hadir sebagai serikat anak-anak yang penting dalam satu sistem. Bagi saya, dalam sajak ini, Jokpin seperti sedang mengilustrasikan bagaimana sebuah elemen terkecil dalam suatu sistem bekerja.
Kita dapat melihat setiap anak yang berserikat itu bekerja sesuai fungsi mereka. Mari kita baca kembali: Anak buah/yang hijau muda/gemetar/dibelai anak angin/di tangkai tua.//Anak air di bawah pohon/berdebar menunggu/anak daun/terlepas/dari anak cabang/dan kembali/menjadi anak bumi.//Aku mau/jadi anak susu/bagi buah kopi/yang meranum/di batang tubuhmu. Dalam alur sajak ini, setiap kejadian memiliki kausalitas yang erat berkaitan.
Setiap anak dalam sajak ini yang dituturkan dengan imajis menjalani peran mereka, tanpa saling menghancurkan. Melainkan selalu menyokong kehidupan satu sama lain. Mereka tidak saling menindas. Sangat egalitarian. Dengan kata lain, sajak ini sangat sosialis.
Lantas, untuk menjawab pertanyaan awal dari tulisan ini, mengenai apakah Jokpin melakukan pergeseran makna, penyimpangan makna, atau penciptaan makna baru atas idiom-idiom atau ungkapan-ungkapan yang menjadi judul sajaknya? Sebaiknya kita tidak perlu mengonkretkan jawabannya. Sebab menikmati sajak adalah mengalami sajak itu sendiri, apakah dengan menggunakan seluruh indera kita, menjadikan ruang dialektika dengan segenap wawasan kita, atau cukup menikmatinya sambil menikmati secangkir teh di kala senja.[]





