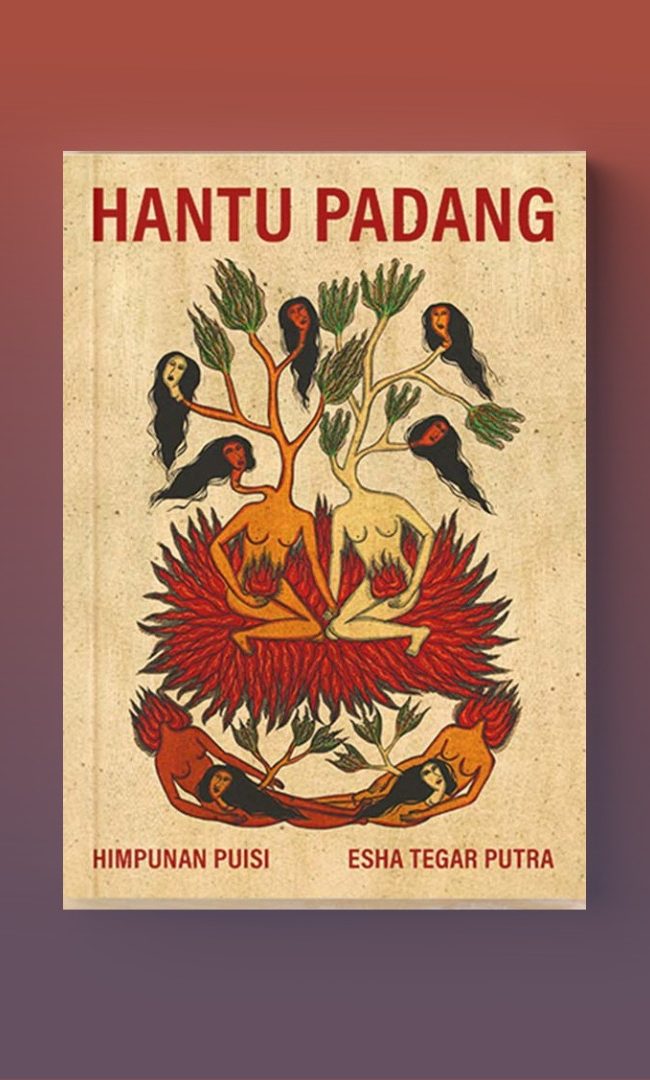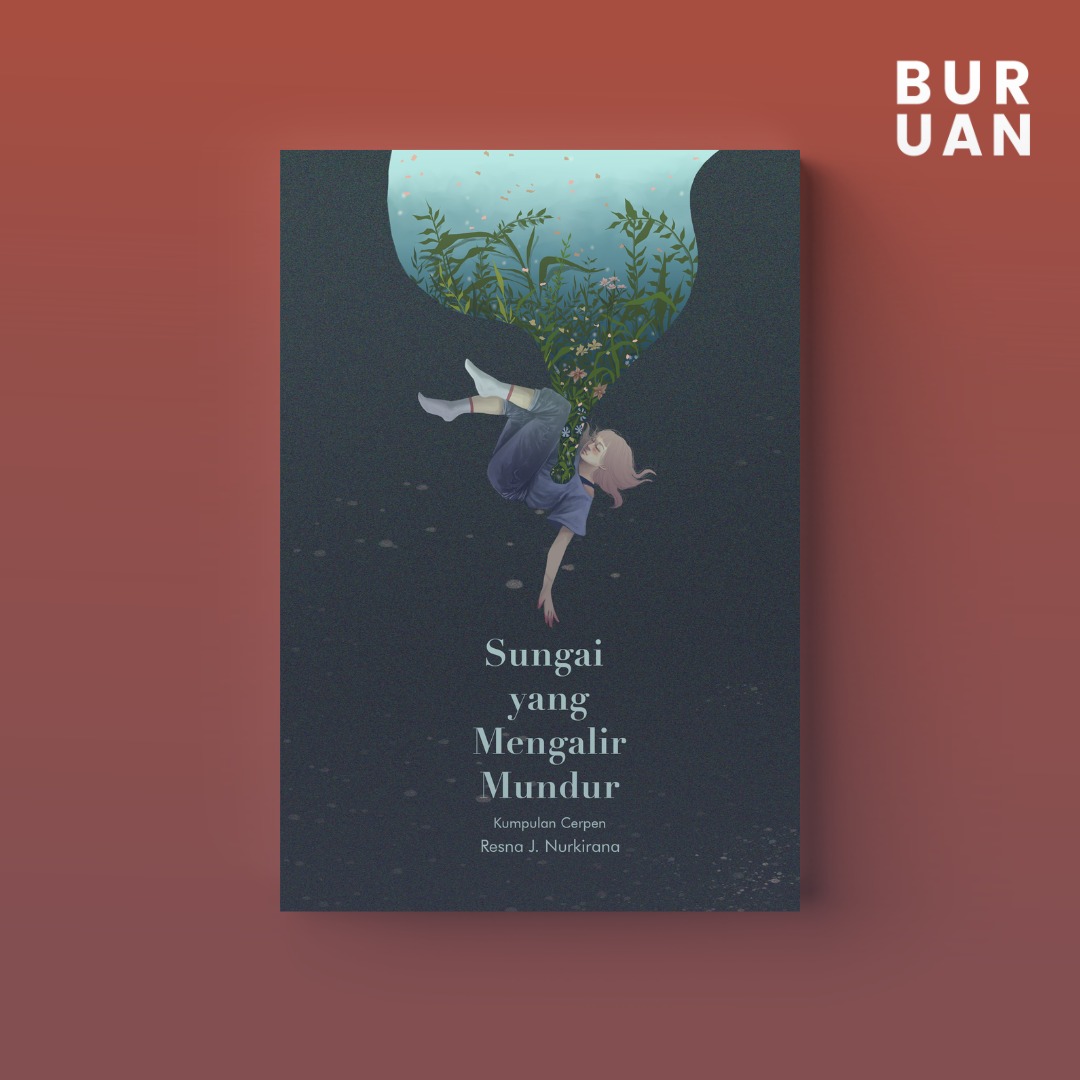
Membaca Cerita Pendek di Era Media Sosial
Kata Pengantar kumpulan cerpen Sungai yang Mengalir Mundur karya Resna J. Nurkirana
Kawan saya, yang kini menjadi seorang guru, Resna J. Nurkirana, menerbitkan kumpulan cerita pendek pertamanya di era ketika kita, menurut sebuah penelitian, membuka ponsel kira-kira enam jam per hari. Sebagian orang bahkan bisa menghabiskan waktu separuh hari bermain media sosial. Di era digital ini, tidak sedikit yang mengeluhkan betapa sulitnya lepas dari kesenangan membuka media sosial. Bermain-main di dunia digital memang bikin kecanduan meskipun di saat yang sama kita juga memahami dampak buruknya. Bukankah tidak sedikit pula orang yang menghapus akun atau hiatus dari media sosial demi menyembuhkan konsentrasi bahkan mungkin mentalnya?
Setiap detik kita disuguhi berbagai narasi yang serba ringkas, baik dalam bentuk video TikTok, reels Instagram, video pendek Youtube, utasan Threads dan seterusnya. Persoalannya adalah, sebagaimana sering dikeluhkan, ketika narasi-narasi serba ringkas itu lebih banyak menghadirkan kedangkalan daripada kedalaman. Sekalipun kita bisa menganggap bermain media sosial sebagai hiburan belaka, tapi itu tidak menutup kenyataan bahwa gelombang narasi singkat yang mengejar keterbacaan cepat dan viralitas itu mengandung dampak serius.
Bagaimanapun juga, media sosial dengan segala intrik keringkasan narasinya telah berkontribusi besar pada peningkatan apa yang disebut para ilmuwan digital sebagai “mentalitas instan”, yang membuat kita terbiasa mencari kepuasan cepat (quick gratification), yang di saat yang sama membuat kita semakin berat untuk menjalani suatu proses bertahap dengan sabar dan merasa suatu upaya untuk melakukan refleksi panjang sebagai hal yang ribet. Konsentrasi dan perhatian pikiran kita terus-menerus dilatih dalam durasi pendek dan karena dimensi kongnitif kita terbiasa dengan potongan demi potongan narasi, bahkan semua itu hanya sekadar lewat, otak kita jadi sulit menyimpan pengetahuan mendalam. Hari terasa penuh informasi, tapi minim pengalaman yang lebih sublim.
Secara sosial, perubahan kualitas berpikir dari pribadi ke pribadi seperti itu, dengan suatu dan lain cara, memudahkan munculnya kecemasan kolektif, mulai dari apa yang sering disebut dengan FOMO (fear of missing out) hingga desakan psikologis untuk segera membuka notifikasi yang masuk ke ponsel; mulai gelisah sendiri kalau terlalu berjarak dari ponsel hingga ketergantungan pada validasi cepat; mulai dari takut ketinggalan meme, gosip, atau challenge terbaru hingga takut tidak segera membeli barang yang lagi promo kilat di e-commerce atau konten “produk lagi diskon besar”; mulai dari kegusaran kalau tidak memberi reaksi cepat hingga akhirnya berada dalam kondisi kelelahan digital.
Meskipun begitu, di tengah tingginya dampak buruk media sosial, justru situasi itu pula yang membuat buku “Sungai yang Mengalir Mundur” ini mendapatkan momentum yang tepat. Tentu ini tanpa bermaksud mengatakan bahwa semua yang berada di media sosial hanya racun digital saja. Ada banyak seni video, misalnya, yang dengan sangat menarik bermain-main dengan durasi pendek di media sosial tanpa kehilangan daya gugahnya pada kesadaran kita. Kita juga tahu bahwa dampak baik paling jelas dari media sosial adalah terciptanya akses luas untuk penyebaran sumber-sumber pengetahuan yang berharga. Kita sudah melihat juga bagaimana gerakan sosial lebih cepat menyebar dan menjadi suara yang sangat berpengaruh dalam perjuangan para aktivis. Tak hanya menghubungkan orang-orang lintas wilayah dan budaya, media sosial juga telah berkontribusi memungkinan terjadinya solidaritas lintas negara dalam isu-isu global. Belum lagi, terjadinya respons cepat cepat dalam krisis-bencana dalam menyebarkan informasi darurat dan mempercepat bantuan kolektif serta gotong-royong via medium digital juga karena media sosial. Tentu tak lupa kita berhutang pada media sosial karena wahana digital ini juga menjadi ruang yang terbuka lebar bagi ekspresi seni, humor, literasi, hingga penyebaran komunitas daring yang berfokus pada kepedulian sesama kelompok marjinal.
Semua cerita pendek dalam buku ini benar-benar pendek, dalam artian jauh lebih pendek dari cerita pendek umumnya, katakanlah, yang biasa kita baca di koran-koran konvensional. Kalau salah satu pengertian cerita yang pendek adalah cerita yang dapat dibaca sekali duduk, maka kita benar-benar akan menyelesaikan satu cerita dalam sekali duduk tanpa harus istirahat sejenak. Cerpen pertama dalam buku ini saya selesaikan pertama kali sembari menunggu air yang direbus hanya untuk membuat secangkir kopi. Cerpen terakhir saya selesaikan dalam pembacaan kedua kalinya sambil menunggu semangkuk sop yang saya pesan tidak terlalu panas.
Keringkasan cerita-cerita yang lebih pendek seperti itu tentu ada, meski tidak semua cerita yang lebih pendek akan seperti itu. Tentu bagi orang yang senang menyetarakan ritme media sosial dengan produk budaya lainnya, cerita ringkas akan dianggap lebih cocok dengan publik hari ini. Hal itu bisa saja menjadi kelebihan cerita dalam buku ini tapi hal penting lainnya tentu jangan sampai diluputkan. Cerita ringkas seperti dalam buku ini cenderung mengarahkan kita sebagai pembaca pada satu kesan dominan dan karena itu ledakan konflik di dalam terasa lebih menghentak. Cerita yang seperti itu dapat meninggalkan kesan emosional yang dalam justru karena kita ditarik sebentar ke suatu tegangan peristiwa dan kemudian dengan berakhirnya cerita dengan cepat kita dilemparkan kembali ke kesadaran awal. Dalam sebuah cerita, pilihan tokoh Karyo untuk menghancurkan pendil berisi ari-ari anaknya karena kemandegan pikirannya dalam mempersiapkan kebutuhan acara selamatan yang harus dilakukan itu benar-benar meninggalkan pedih yang mendalam, apalagi sejak awal hingga akhir cerita diisi dengan kesan mendesak sekaligus tak berdaya dari tokoh-tokoh di dalamnya.
Sementara itu, di cerpen yang berbeda, keringkasan sebuah cerita juga dapat memaksimalkan ambiguitas dari akhir suatu cerita. Dengan tidak menuntaskan banyak detail dan ditambah lagi dengan model akhir cerita yang bersifat terbuka, cerita dapat berakhir dengan berbagai kemungkinan tafsir. Dalam cerpen yang berbeda, ketidaktuntasan sejumlah detail, bahkan mungkin penjabaran mendalam atas hal-hal tertentu, bukanlah sebuah kelemahan ketika fokus pada konflik dan solusi yang digambarkan sudah cukup membuat kita bertanya kembali tentang kisah lain di balik cerita yang sudah berakhir. Tidak lengkapnya informasi yang kita ketahui tentang apa yang membuat tokoh aku merasa mual dan tidak lengkapnya informasi tentang siapa suami tokoh Aku yang dipandang-pandang oleh pekerja di rumahnya, Tinah, ditambah lagi cerita yang ringkas itu juga dibagi menjadi beberapa bagian cerita yang lebih pendek, memperdalam kualitas ambiguitas cerita yang ditampilkan. Apalagi jika ketidaklengkapan itu kita kaitkan dengan katakanlah ketidaklengkapan informasi tentang tatapan seperti apa yang dilakukan Tinah kepada suami si tokoh aku, membuat cerita penuh oleh semacam teka-teki yang berkaitan dengan psikologi tokoh; teka-teki yang lebih menuntut kita untuk menggeser-geser sendiri kemungkinan demi kemungkinan jawabannya.
Keringkasan cerita juga mendorong penulis untuk sedikit-banyaknya bermain-main dengan cara penceritaan, sesederhana apapun itu. Dengan tidak terlalu terikat pada kesinambungan plot yang lebih panjang, penulis tampak berusaha lebih banyak membangun suasana baik lewat dialog ataupun deskripsinya sendiri. Konstruksi suasana itu, dalam hasil yang terbaiknya, akan berdampak besar pada kekuatan impresi yang kita dapatkan dari tegangan antar tokoh. Atmosfer yang melingkupi tokoh-tokohnya dapat menjadi sajian utama yang diberikan kepada pembaca. Dalam cerpen yang lain, separuh cerita berlangsung dalam isi surat yang ditulis Sura untuk Adam. Meski Adam tidak pernah membaca surat itu dan ia tak benar-benar tahu apa yang dirasakan Sura, tapi kita sebagai pembaca merasakan betapa peliknya dan dilemanya perasaan yang dipendam Sura justru karena kita membaca isi suratnya. Dan kita juga jadi ikut menimbang-nimbang sendiri apakah sikap Adam telah menyelamatkan dirinya dan Sura dalam hubungan yang tidak jelas atau justru semakin memperparah ketidakjelasan hubungan kedua tokoh itu.
Perlu buru-buru saya sampaikan bahwa para pembaca buku ini bisa menelusuri lebih jauh lagi dampak dari keringkasan cerita-cerita di dalamnya, bahkan secara politis. Ada sejumlah cerita lainnya yang akan menghadirkan tegangan tertentu dengan cara yang berbeda. Yang ingin saya tekankan adalah perihal kontribusi cerita-cerita ringkas dalam buku ini, apapun itu visi ceritanya, dalam memberikan kepada kita suatu pengalaman untuk merenungkan apa-apa yang telah diceritakan dengan berbagai strategi. Sekalipun panjang cerita-cerita di sini sesuai dengan “semangat zaman digital” yang serba ringkas, tapi keringkasan buku ini tidak membuat peristiwa-peristiwa di dalamnya lewat begitu saja seperti sebagian besar postingan yang bergerak cepat di ponsel kita. Bagi pembaca yang terbiasa dengan segala yang serba disediakan tanpa harus merefleksikan lebih jauh, seperti potongan video Youtube yang hilang konteks, mungkin saja akan kecewa dengan sejumlah cerpen. Dan sesungguhnya itulah yang membuat buku ini lebih berarti: keringkasannya malah menciptakan jeda dalam pikiran kita untuk kembali mengingat dan merenungkan solusi konflik di dalamnya. Durasi pendek untuk setiap kejadian tidak meladeni kebiasaan kita yang terlanjur mudah dibawa lewat oleh keterburu-buruan dan keseragaman atmosfer di media sosial.
Beberapa waktu setelah membaca buku ini saya masih kepikiran soal pilihan tokoh Karyo menghancurkan pendil yang berisi ari-ari anaknya. Desakan mertuanya seperti makin diperdalam dengan cepatnya peristiwa berlangsung hingga akhir. Saya berkali-kali membayangkan seberapa kerasnya kebuntuan Karyo sehingga ia melampiaskannya pada pendil itu. Begitu juga, di cerpen yang berbeda, kemarahan tokoh Suami pada tokoh Sutar terasa makin membara seiring dengan padat-cepatnya ceritanya berlangsung dengan latar waktu yang sebenarnya terjadi selama berminggu-minggu. Dan ini membuat saya seperti tak bisa mengambil nafas panjang dulu dan langsung tersentak-terperangah dengan pilihan tragis yang diambil tokoh Sutar; sentakan yang ternyata bergema panjang di dada saya. Sementara itu, di cerpen lainnya, pilihan tokoh aku untuk mengambil jerigen bensin dan korek gas di akhir cerita membuat saya langsung berpikir bahwa ia akan membakar bapaknya dan seorang anak malang, padahal bisa saja maksud si tokoh bukan itu; namun keringkasan cerita itu terlanjur menjadi semacam intrik yang menguji daya asosiasi saya terhadap alur peristiwa pembakaran manusia yang saya baca tak berapa lama sebelumnya dalam cerpen yang dibaca sekali duduk itu; saya jadi berpikir kembali perihal bagaimana kita mudah menciptakan kesimpulan hanya karena suatu kesamaan pola cerita.
Demikianlah, saya senang sekali mendapati bahwa sekumpulan cerita yang cukup pendek dalam buku ini, di tengah gelombang narasi ringkas yang kita dapatkan selama sekian jam per hari di media sosial, masih meninggalkan denyut renungan di kepala saya. Judul buku ini terasa sangat tepat dalam konteks bahwa keringkasan buku ini “mengalir mundur” melawan arus keringkasan media sosial dengan cara membawa kita ke salah satu hulu karya seni: dengan segala keterbatasan mediumnya, seni terus berupaya memberikan kepada kita suatu fasilitas untuk latihan merasakan empati pada orang lain dan menimbang-nimbang makna hidup ini. Semoga kawan saya, Resna, selalu tertantang untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan lain dari keringkasan sebuah cerita pendek dan terus bersuara tentang yang tak tersuarakan.
Saya ingin menutup catatan ini dengan sebuah impresi pribadi pada cerita pendek berjudul “Jalan ke Luar”. Karena bau badannya yang tidak kunjung berhenti bahkan sejak lahir, tokoh Zul terpaksa memilih berhenti ke sekolah dan memutuskan untuk membantu ayahnya yang bekerja sebagai buruh pabrik sawit. Sebagai warga Sumatra yang menyaksikan sendiri betapa semakin rusaknya lingkungan alam dan lebih banyak lagi mirisnya kehidupan masyarakat karena dampak perkebunan sawit, bau badan itu benar-benar terasa sebagai sebuah metafora yang tepat untuk menggambarkan persoalan ketidakadilan. Seperti bau badan yang dialami tokoh Zul, ketidakadilan ekonomi di daerah yang penuh oleh perkebunan sawit juga sudah menubuh, seperti bawaan lahir yang sulit disembuhkan, yang tidak hanya menjadikan orang-orang kecil tak berdaya sebagai pihak yang disingkirkan tetapi pada akhirnya menyingkirkan diri sendiri. Dan seperti tokoh Zul yang punya penyakit bau badan yang terasa bagai kutukan, rakyat kecil di dalam kuasa kapitalisme global juga tidak pernah lepas dari kutukan ketimpangan ekonomi: kalaupun mereka menemukan jalan ke luar, tetap saja itu bukan jalan keluar yang sebenarnya. Seperti nasib melarat yang turun-temurun, setiap jalan ke luar tidak membawa ke mana-mana kecuali membuat mereka kembali pada lingkaran setan yang sama. Dengan menjadikan tokoh Zul hanya berkeinginan untuk meneruskan pekerjaan ayahnya sebagai buruh kecil, meneruskan kemelaratan yang sama, cerpen “Jalan ke Luar” ini seperti mengatakan bahwa yang kita butuhkan saat ini adalah jalan keluar.