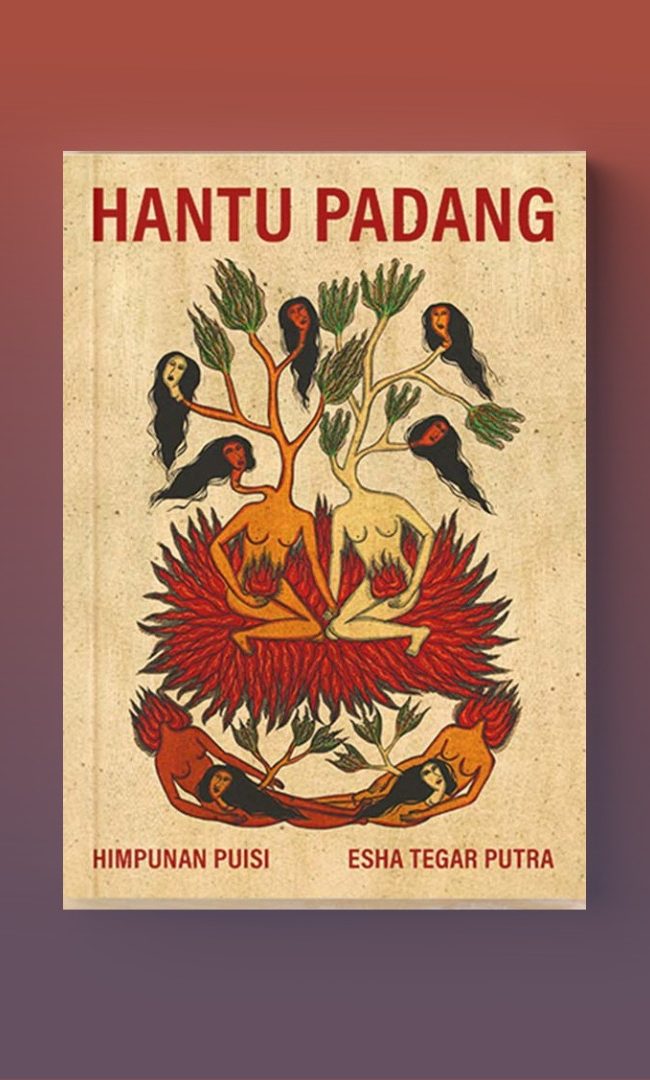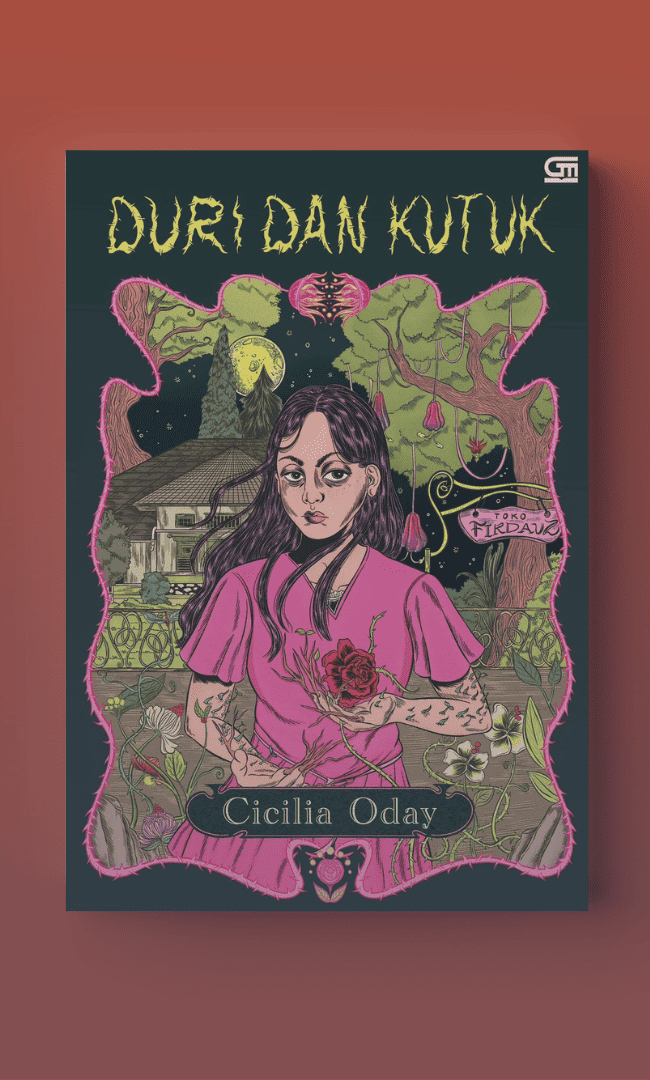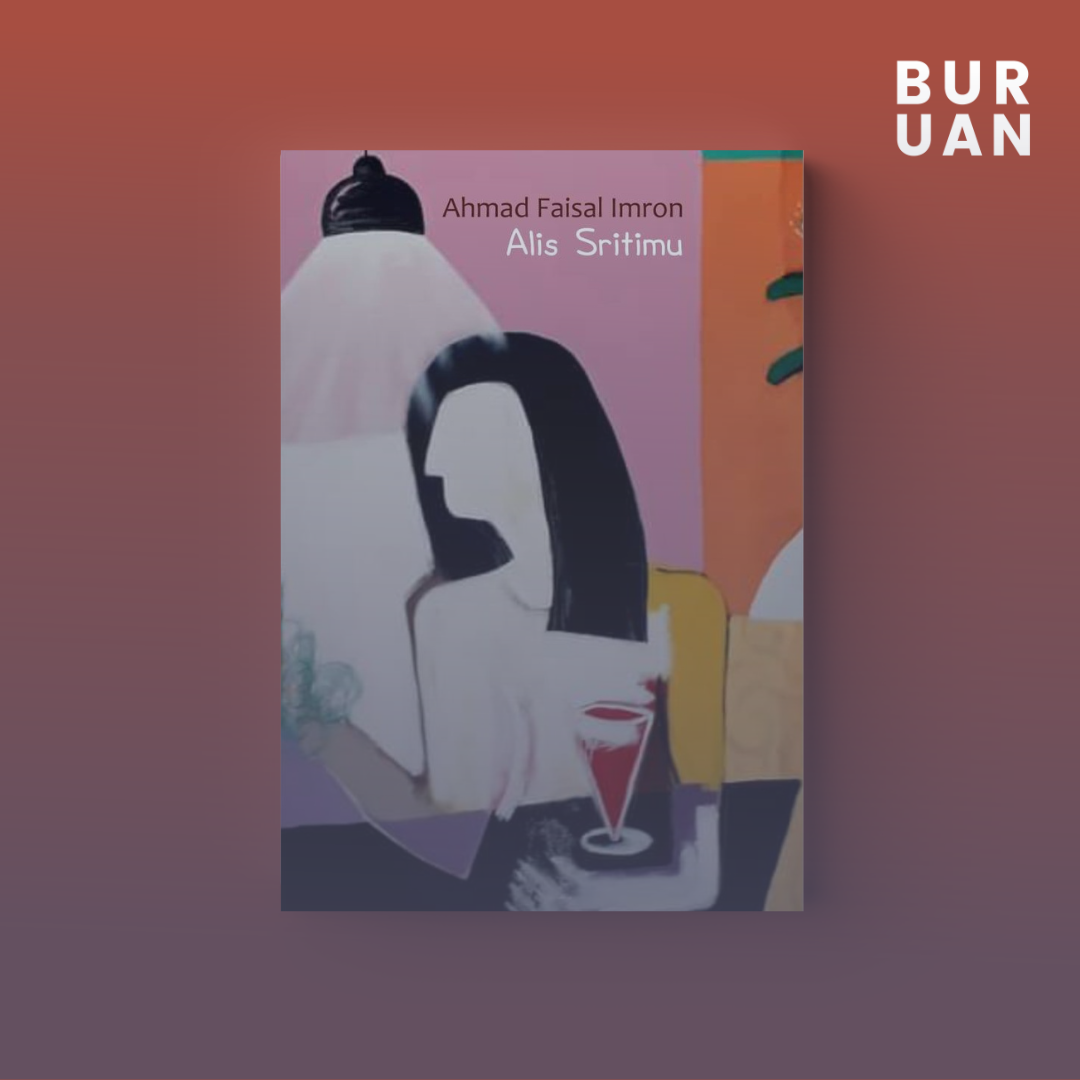
Petala Makna dalam Buku Puisi Alis Sritimu Karya Ahmad Faisal Imron
*Esai ini didiskusikan dalam gelaran Bukan Jumaahan Akbar di Perpustakaan Ajip Rosidi, Bandung, 10 Oktober 2025.
Guru menulis puisi saya pernah bilang, kurang-lebih, begini: “Teruslah menulis puisi, tentang apa saja; ada banyak hal yang bisa ditulis jadi puisi. Tapi jangan dulu menulis puisi cinta. Puisi cinta itu paling sulit ditulis justru karena ia paling sering dituliskan.”
Karena ‘paling sering’ ditulis, sudah barang tentu puisi cinta, dengan segala variannya, paling mudah ditemukan. Ambillah buku puisi mana pun, karya siapa pun, dari periode kapan pun, buka, di dalamnya pasti ada puisi cinta. Tengok puisi-puisi yang berserakan di media sosial, atau di rubrik sastra luring maupun daring, apa yang kebanyakan ditulis para penyair itu? Puisi cinta! Ah, indah betul semesta perpuisian kita: selalu penuh dan berlimpah cinta.
Tapi, apabila kita mengambil jarak dari fenomena puisi cinta yang ada di mana-mana itu dan melihat dengan lebih saksama, paling tidak ketika saya melakukan itu, timbul pertanyaan berikut: Apa saja yang telah ditawarkan oleh puisi-puisi cinta itu? Dan dari yang ‘apa saja’ itu, karena puisi cinta terus ditulis, adakah hal baru yang ditawarkan oleh puisi-puisi cinta itu? Kalau iya, ada sesuatu yang baru di dalam puisi-puisi cinta yang banyak sekali itu, kita boleh bersyukur karena ada banyak puisi cinta yang bisa memperkaya kesadaran, pemahaman, cara pandang, aspek, dimensi, dll., kita tentang cinta. Sebaliknya, kalau tidak ada sesuatu yang baru di dalam puisi-puisi cinta yang amat sangat banyak itu, lalu untuk apa puisi cinta (terus) ditulis?
Untuk apa puisi-puisi cinta itu ditulis kalau hanya mengulang-ulang sesuatu yang sudah ditulis, yang itu-itu juga, semisal tentang ‘cinta pada pandangan pertama’, ‘cinta bertepuk sebelah tangan’, ‘cinta tak harus memiliki’ atau konsepsi-konsepsi cinta lainnya yang sudah kita kenal? Di titik ini timbul pertanyaan: “Memangnya, ada sesuatu yang baru?” Dari sejak manusia terantuk pikir tentang cinta, ditambah sejak manusia punya perangkat bahasa, wabil khusus perangkat aksara, kemudian mereka mulai menuliskan cinta yang terantuk-antuk di dalam pikiran mereka itu, sudah berapa puisi cinta yang ditulis? Sepanjang sejarah peradaban manusia, kalau mau dibilang, sebenarnya para penyair menulis tentang cinta yang itu-itu juga, bukan?
Barangkali terkait perkara inilah guru saya menasihati saya agar jangan dulu menulis puisi cinta. Dalam pertimbangan saya, barangkali alasannya adalah menulis puisi cinta butuh pengetahuan yang memadai. ‘Memadai’ di situ tentu saja abstrak, tidak tentu takarannya. Tapi, kalau menyangkut, misalnya, pengetahuan ihwal referensi, penting juga mempertimbangkan sebanyak apa puisi cinta yang sudah kita baca; sebanyak apa kita sudah meraup dan melahap, menciduk dan menenggak, puisi-puisi cinta yang sungguh amat sangat banyak itu. Agar apa? Agar kita bisa tahu—secara memadai yang tidak jelas takarannya itu—puisi cinta macam apa yang sudah (dan pada gilirannya, yang belum) ditulis para penyair sebelum kita, bagaimana cinta dituliskan di dalam puisi oleh para penyair sebelum kita; dan, yang agaknya penting bagi setiap penyair, ketika menulis puisi cinta, agar tidak melakukan pengulangan perspektif, gaya ungkap, stilistika, dll.
Sedikit-banyak, penyair harus siaga: Jangan-jangan puisi cinta seperti ini sudah pernah ditulis; siapa tahu puisi cinta seperti itu sudah pernah dicatat. Lantaran cinta bukanlah tema baru, taruhan penyair ketika menulis puisi cinta adalah kebaruan dalam perspektif atau gaya ungkap atau stilistika. Dalam aspek-aspek itulah kebaruan bisa terus-menerus diupayakan. Barangkali cinta yang ada di dunia ini memang cuma cinta yang itu-itu juga; tapi cara pandang manusia terhadap cinta yang itu-itu juga bisa amat sangat bermacam-macam, berjenis-jenis, berbagai-bagai, dan agregatnya bisa tak hingga.
Barangkali, salah satu keajaiban cinta adalah ia, dari dirinya yang esa, bisa melahirkan sesuatu yang ananta.
***
Ahmad Faisal Imron, yang akrab saya sapa Kang Fai, seorang penyair, pemusik, pelukis, ajengan, baru saja merilis buku puisi terbarunya, Alis Sritimu (2025). Ini adalah buku puisinya yang ketiga setelah Maliun Hawa (2007) dan Langit Lemburawi (2012). Kang Fai adalah guru saya dalam menulis puisi juga, barangkali yang bersangkutan tidak mengakui dan saya hanya mendaku-daku diri, adalah guru spiritual saya.
Ketika Kang Fai bilang bahwa Alis Sritimu ingin diterbitkan oleh penerbit Trubadur yang saya kelola, sudah barang tentu saya girang. Tanpa ba-bi-bu, saya mengiyakan. Lebih girang lagi ketika, dalam proses penerbitannya, saya diajak terlibat untuk menyunting manuskrip tersebut, meskipun peran saya hanya menyangkut hal-hal renik semisal saltik atau logika kalimat. Intinya, saya senang; menerbitkan buku puisi guru saya sendiri adalah suatu kehormatan bagi saya.
Pertama-tama yang menarik di dalam buku puisi Alis Sritimu, sebagaimana di dalam buku puisi Kang Fai yang sebelum-sebelumnya, adalah stilistika. Bahasa dan gaya bahasa adalah sesuatu yang unik. Sebagai medium komunikasi, bahasa memiliki seperangkat sistem; dan sebagai sesuatu yang sistemik, tentu bahasa memiliki perangai yang agak-agak pejal. Tapi, sebagai medium karya sastra, bahasa yang sistemik serta pejal sekalipun bisa menjadi lentur, lunak, empuk, encer. Sebagai medium karya sastra, bahasa memungkinkan lahirnya stilistika, gaya bahasa yang unik dari tiap-tiap penggunanya, dalam hal ini para sastrawan. Sastrawan yang mumpuni, salah satunya, pasti memiliki stilistika yang khas miliknya sendiri. Diktum ini boleh-boleh saja didebat.
Mencermati stilistika di dalam buku puisi Alis Sritimu, apalagi bagi mereka yang sudah akrab dengan puisi-puisi Kang Fai sebelumnya, barangkali sedikit-banyak akan merasakan adanya perubahan. Di dua buku puisi sebelumnya, Maliun Hawa dan Langit Lemburawi, puisi- puisi Kang Fai terasa subtil, padat, serius, dan prismatik; diksi dipilah dengan sangat ketat, metafora dibentuk secara cermat, dan imaji dibangun sedemikian rupa hingga tampak ajek. Di dalam Alis Sritimu, terjadi semacam pergeseran stilistika dari yang subtil ke yang terang, dari yang padat ke yang cair, meskipun puisi-puisi itu tetap serius, prismatik, dan imaji-imaji yang dibangun tetap solid.
Citraan-citraan alam banyak digunakan oleh Kang Fai untuk membangun imaji di dalam puisi-puisinya. Saya menduga, kampung Lemburawi di Bandung Selatan punya peran dalam hal ini.
jemari matahari mengelus kelopak citrina
serta dipersilakannya mencipta lesung kolam
sebelum seekor katak bermimpi mengusiknya
(puisi “Puisi, Lorca, dan Kelopak Citrina”, hlm. 2)
Penyair, dengan menggunakan kata-kata, bisa mencipta-ulang realitas. Contohnya dapat kita lihat pada kutipan puisi di atas. Kita tentu akrab dengan gambaran ‘lingkar air yang terbentuk di atas permukaan air lantaran ada sesuatu mengusik permukaan air yang semula geming itu’; kita akan menyebut fenomena itu sebagai “riak”. Tapi, di dalam puisi, “riak” sebagai suatu fenomena bisa dicipta-ulang, misalnya, sebagaimana yang dilakukan Kang Fai dalam puisi di atas, menjadi “lesung kolam”.
Mengapa penyair merasa perlu mencipta-ulang realitas? Karena kebanyakan manusia cenderung kehilangan perasaan takjub, pukau, pesona, ketika dihadapkan dengan realitas yang telah menjadi akrab, karib, dan lazim baginya. Berapa orang yang masih dihinggapi perasaan tercengang ketika melihat riak air di sebuah kolam atau telaga? Berapa orang yang masih terpana ketika mendapati dedaunan di ranting pohon berguncang dan berdesir saat disentuh semilir angin? Saya kira tidak banyak. Tapi, ketika realitas yang telah menjadi biasa-biasa saja itu dicipta-ulang, ada kemungkinan perasaan takjub, pukau, dan pesona bisa kembali terpetik. Barangkali tidak ada sesuatu yang timbul di dalam benak kita ketika kita membaca frasa “riak air”; tapi, ketika “riak air” dicipta-ulang menjadi “lesung kolam”, boleh jadi ada sesuatu yang ‘beriak’ di dalam benak kita ketika kita membaca frasa tersebut.
Pertanyaannya, mengapa kita harus memelihara dan apa pentingnya memelihara perasaan takjub, pukau, dan pesona di dalam benak kita? Saya akan meminjam dawuh sang Hujjatul Islam, Imam al-Ghazali, untuk menjawab pertanyaan tersebut: “Orang yang jiwanya tidak tergerak oleh semilir angin, semerbak wangi bunga-bunga, dan suara seruling musim semi, adalah dia yang telah kehilangan jiwanya yang sulit terobati.” (Ihya’ ‘Ulum al-Din, 2/275).
Kurang-lebih, saya ingin mengatakan, barangkali salah satu tugas (sangat berat) penyair adalah menjaga batin manusia agar tidak kehilangan denyut jiwanya. Sebab, apabila manusia kehilangan jiwanya, masihkah ia bisa disebut ‘manusia’, makhluk Tuhan yang paling sempurna? Apabila manusia kehilangan jiwanya, masihkah ia sempurna sebagai makhluk? Manusia semestinya tetap terpesona ketika melihat gerak luwes seekor kucing atau liuk lentur seekor ikan untuk yang ke-1001 kali sebagaimana ia terpesona ketika melihatnya pertama kali; seorang istri/suami semestinya tetap jatuh cinta kepada pasangannya setelah melewati sepuluh, dua puluh, tiga puluh, empat puluh, lima puluh tahun pernikahan mereka, dengan cinta yang sama besar seperti ketika ia pertama kali memandang pasangannya dan merasa serta-merta dunia disulap menjadi surga dalam sekejap mata.
ya, kita benar-benar abadi
menjadi gerimis menjelang pagi
berbahagialah, melicja
(puisi “Menjelang Pukul Tiga Dini Hari”, hlm. 12)
Saya cuplik bagian puisi di atas karena ingin bicara tentang aspek lain yang juga menarik di dalam buku puisi Alis Sritimu: paradoks. Kutipan bait itu bisa menjadi contoh bagaimana paradoks dikonstruksi dengan sedemikian cermat serta penuh perhitungan. Aku-lirik berujar, ‘kita benar-benar abadi’, dan untuk menggambarkan bahwa ‘kita benar-benar abadi’ ini aku- lirik mengilustrasikannya dengan ‘gerimis menjelang pagi’.
‘Gerimis’ adalah sesuatu yang rentan, ia berada di antara dua kontras yang tegas, ia ada di antara dua titik ekstrem, yakni ‘hujan’ dan ‘tidak hujan’. Gerimis adalah hujan dalam intensitas yang kecil; sedikit saja intensitasnya bertambah, maka ia sudah bukan lagi gerimis, ia sudah berubah menjadi hujan; sebaliknya, sedikit saja intensitasnya berkurang, maka ia sudah bukan lagi gerimis, ia sudah berubah menjadi tidak hujan. Demikian pula dengan ‘menjelang pagi’ atau kita bisa menyebutnya sebagai periode ‘subuh’. Subuh ini ringkas dan rapuh: mundur sedikit, ia masuk ke dalam periode malam; maju sedikit, ia masuk ke dalam periode pagi, atau katakanlah, siang. Subuh berada di antara kontras gelap-hari dan terang-hari yang secara durasi lebih panjang.
Padanan-padanan inilah—‘gerimis’, ‘menjelang pagi’ (subuh)—yang dipilih aku-lirik untuk menegaskan ke-‘abadi’-an; ia menggunakan sesuatu yang fana, yang sementara, dan yang lekas lenyap justru untuk menandai keabadian yang tidak fana, tidak sementara, dan tidak lekas lenyap. Di sinilah paradoks beserta kedalaman terbentuk.
***
Sebagaimana yang dituturkan oleh Kang Fai sendiri, Alis Sritimu menghimpun puisi- puisi cinta yang, jika dibandingkan dengan buku sebelumnya, Langit Lemburawi, secara pengucapan relatif cair, renyah, dan ada manis-manisnya. Ada banyak larik dan bait yang quotable, cocok dikutip dan dijadikan caption di Instagram. Berikut saya nukilkan tiga saja dari bagian-bagian yang, menurut saya, quotable:
sejak adam dan hawa diturunkan ke bumi
sejak itulah sejarah rindu dimulai
(puisi “Ayat Pertama”, hlm. 4)
minta tolonglah pada rindu
jika engkau tak bisa memeluk kekasihmu
(puisi “Minta Tolonglah pada Rindu”, hlm. 17)
percayalah, hanya ada dua alam
yang sebenarnya kau huni, satu: alam pikiranku
dua: alam muasalmu, yaitu sebilah iga kiriku
(puisi “Beberapa Bait Kesedihanmu”, hlm. 21)
Sudah saya katakan di atas, kumpulan puisi ini ‘ada manis-manisnya’. Tapi, tidak sekadar bermanis-manis, di dalam puisi-puisi cintanya Kang Fai berupaya mengetengahkan cara pandang lain tentang cinta. Ambil contoh nukilan terakhir yang saya kutip di atas, puisi berjudul “Beberapa Bait Kesedihanmu”.
Puisi itu bicara perihal relasi cinta; kau-lirik sebagai objek (yang di)cinta(i) dari aku-lirik sebagai subjek (yang men)cinta(i). Dikotomi ‘kau-aku’ di situ mengandaikan adanya keterpisahan, dan keterpisahan mengandaikan adanya interval, jeda, jarak. Tapi, sungguhan adakah interval itu, jeda itu, jarak itu, di antara sepasang kekasih, di antara kau dan aku? Puisi “Beberapa Bait Kesedihanmu” menunjukkan bahwa interval, jeda, dan jarak itu sesungguhnya tidak ada. Sebab, sebagaimana yang diungkapkannya, “hanya ada dua alam/ yang sebenarnya kau huni, satu: alam pikiranku/ dua: alam muasalmu, yaitu sebilah iga kiriku//”
Kita bisa melihat bahwa ‘alam’ yang dihuni oleh kau-lirik bukanlah ruang-berjarak melainkan ruang-tanpa-jarak dari aku-lirik, sebab alam yang dimaksud adalah ‘pikiranku’ dan ‘sebilah iga kiriku’, yakni pikiran aku-lirik dan sebilah iga kiri aku-lirik. Sudah barang tentu ‘dua alam’ itu adalah loka yang lekat dengan aku-lirik, tanpa jarak dari aku-lirik, bahkan merupakan bagian dari eksistensi aku-lirik. Alhasil, kalau kau ada di dalam pikiranku, kalau muasalmu adalah sebilah iga kiriku, berarti kau adalah bagian dari diriku; secara esensi kau ada di dalam aku, secara hakikat kau tidak ada di luar aku; kau tidak ke mana-mana, kau dekat sekali denganku, amat sangat dekat denganku.
Belum lagi apabila kita meletakkan dan menafsir relasi cinta kau-aku tersebut dalam stasiun atau maqom transendental; kita bisa membacanya tidak saja sebagai relasi cinta dalam derajat horizontal sesama-makhluk, melainkan juga sebagai relasi cinta dalam derajat vertikal makhluk-khalik.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلِْنَْٰسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِۦ نَفْسُهُۥ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ
“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya,
dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya” (Q.S. Qaf: 16)
Sebagai Kekasih, kurang dekat dan lekat apa Tuhan dengan kita? Bukankah Dia bisa ‘mengetahui apa yang dibisikkan’ oleh hati kita karena Dia ada di dalam pikiran kita? Tentu saja, dengan catatan bahwa ‘ada di dalam pikiran’ ini bukan berarti ‘diciptakan oleh pikiran’. Dan bukankah karena Dia ada di dalam pikiran kita berarti Dia berada tanpa jarak dengan kita? Demikianlah, puisi tersebut bisa dibaca sebagai relasi cinta fisik maupun metafisik. Dan saya kira, puisi yang bagus, salah satunya, adalah yang bisa melapangkan ruang pembacaan serta interpretasi, merangkum yang imanen dan transenden, yang duniawi dan ukhrawi, yang insaniah dan ilahiah.
Untuk melihat bagaimana puisi-puisi cinta Kang Fai bisa melapangkan ruang pembacaan serta interpretasi—dan karenanya saya berani bilang bahwa puisi-puisi cinta Kang Fai itu bagus—kita tengok puisi lainnya yang berjudul “Pagi Kedua Puluh Tujuh” (hlm. 58), puisi penghabisan di dalam Alis Sritimu. Saya kutip bait pertama dan terakhirnya:
seandainya hendak pergi, pergilah! namun kau tak akan ke mana-mana
[ . . . ]
seandainya hendak pergi, ya, pergilah
selepas itu, kau tak akan ke mana-mana
Kita bisa membaca aku-lirik yang berbicara kepada kau-lirik di puisi itu dalam spektrum relasi horizontal antar makhluk. Apabila dilihat dari perspektif ini, kita bisa membayangkan, misalnya, seseorang yang, barangkali sedang ribut-ribut dengan kekasihnya, ngomong begini, “Kalau kamu mau pergi, pergi aja sana! Kalau kamu mau putus, ya udah kita putus! Nanti juga kamu bakal balik lagi sama aku!” Sebuah adegan cinta-cintaan.
Tapi kita juga bisa membaca aku-lirik yang berbicara kepada kau-lirik di puisi itu dalam spektrum relasi vertikal Khalik-makhluk. Apabila dilihat dari perspektif ini, bukankah Allah Swt. telah bersabda: “Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali [semua makhluk]” (Q.S. An-Nur: 42); atau: “Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah, dan kepadaNya-lah kita semua pasti akan kembali” (Q.S. Al-Baqarah: 156). Bayangkan Aku-Khalik berkata kepada kau-makhluk, “Kalau kau mau pergi, silakan saja. Pergilah ke mana saja, sekehendak hatimu. Aku ada di mana-mana. Ke mana pun kau pergi, kau tetap berada di dalam kemahaberadaanKu. Itu berarti kau tidak pergi ke mana-mana; kau selalu di sini, bersamaKu, di dalam kemahaberadaanKu.”
Petala-petala makna inilah yang membuat puisi-puisi cinta Kang Fai di dalam Alis Sritimu menjadi bukan sekadar ‘puisi cinta-cintaan’. Puisi-puisi cinta itu bisa ditafsir secara horizontal maupun vertikal. Secara keseluruhan, puisi-puisi di dalam Alis Sritimu memiliki banyak petala makna semacam itu; ia bisa menjadi puisi-puisi cinta yang ringan dan manis, sekaligus bisa menjadi puisi-puisi cinta yang berat dan serius, yang menampakkan kedalaman perenungan, penghayatan, serta kesadaran penyairnya. Tampakan ini bisa berbeda-beda selaras dengan bekal referensial baik yang sifatnya tekstual maupun kontekstual dari pihak pembaca sendiri. Mereka yang memiliki visi, pengetahuan, dan pengertian yang cukup luas barangkali akan mampu menyelam lebih dalam; mereka yang sebaliknya, masih bisa berenang berkecipak di permukaan. Di kedalaman maupun di permukaannya, perairan itu—puisi-puisi cinta itu— bisa tetap menyejukkan.
Kurang-lebih, inilah catatan singkat yang melompat-lompat serta tidak runut dan menyeluruh dari pembacaan dangkal saya terhadap buku puisi Alis Sritimu karya Ahmad Faisal Imron. Buku puisi ini, terlepas dari bahasanya yang sepintas lalu tampak cair, familiar, dan di beberapa bagian bahkan terkesan kekinian, tetap mengisyaratkan suatu kesubtilan.
Wallahu a’lam bishawab. []
8 Oktober 2025