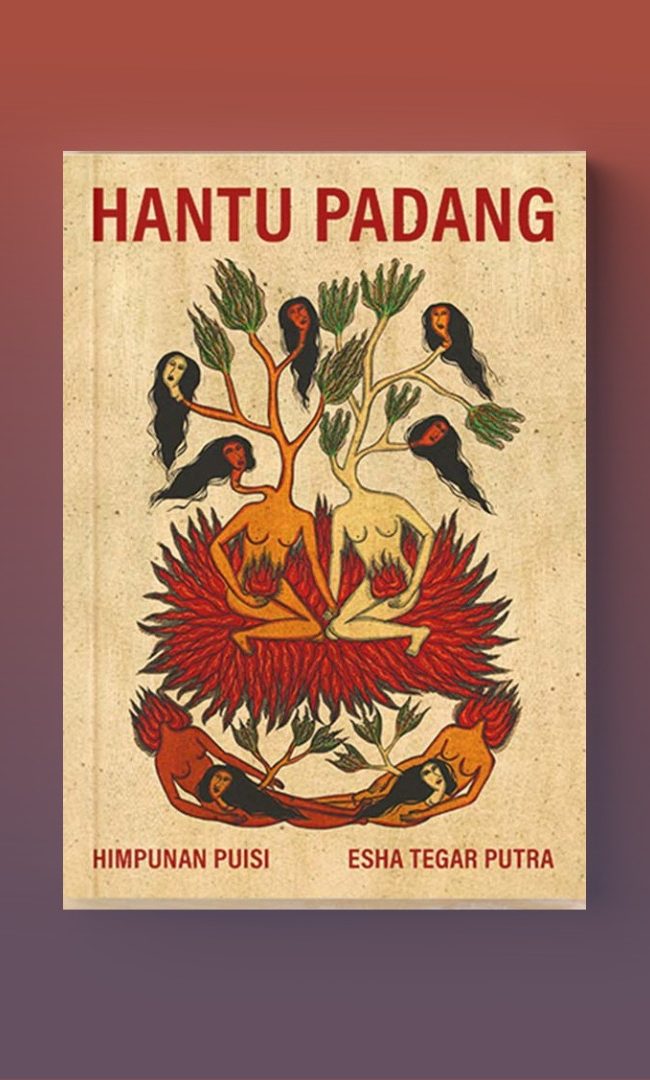Menina-bobokan Jiwa-jiwa Mati dalam Puisi yang Hidup
Saya buka resensi ini dengan kalimat penutup setelah menikmati seluruh puisi Willy: Kepada sisa-sisa kekuatan puisi yang lelah dan terseok mencari jalan pulang/ bait demi bait kegamangan dan kepasrahan yang setia bergandeng tangan/ yakinilah, selayaknya hari kelahiran, ataupun kematian yang menenangkan/ kembalinya ruh pada nyawa-nyawa tanpa jiwa juga patut untuk dirayakan//.
Alasan saya sederhana, karena itulah yang dilakukan Willy Fahmy Agiska pada antologi Seperti Orang Mati yang Hidup (2025). Ia mengawali pembukaan buku puisinya dengan sebuah penutup melalui sajak “tutup” (hlm. 1).
Maka sebelum kita sibuk menapaki lebih dalam petualangan batin Willy Fahmy Agiska yang sarat pencarian esensi rumah dalam antologi ini, izinkan saya menyuguhkan puisi tersebut:
tutup
masukkan
selera humormu
ke toples
lakban, lakban
lihat, seberapa tahan
dunia menahan dirinya
tidak menyingkirkan
Sebelum membaca buku ini, saya terlanjur tuntas membaca dua antologi puisi terdahulu milik Willy, si sulung Mencatat Demam (2018), kemudian Unboxing (2023). Antologi Unboxing merupakan kumpulan puisi yang bagi saya alamak eksperimental. Mulai dari gaya tutur nyeleneh yang mengobrak-abrik romantisme umum puisi, penggunaan diksi-diksi yang dekat dengan industri manufaktur dan istilah-istilah gaul media sosial, rentetan bait (terlampau) panjang hingga nuansa penuh humor satir pun lumrah kita jumpai dalam antologi tersebut. Ketika membuka halaman pertama di buku puisi seperti orang mati yang hidup, saya ingin segera berkesimpulan bahwa puisi “tutup” bukanlah puisi yang menjadi prolog, justru epilog dari gaya Willy yang menjadikan “puisi sebagai wahana komedi putar” di antologi Unboxing.
Namun rasanya kurang adil kalau saya terus-menerus mencari irisan dengan sesuatu yang sudah berlalu. Pasca puisi di atas, saya lanjut membaca antologi ini dengan melapangkan kesempatan bagi semesta macam apa pun yang akan dihadirkan si penyair. Tidak butuh menuggu lama untuk tergugah dalam suasana liris dan syahdu, sajak berikutnya membuat saya merasa seakan-akan kedatangan sahabat lama, yang lantas duduk bersebelahan dan dengan tenang mengajak menyusuri masa lalu.
rumah
waktu dibuka, tak dikira
sudah sesempit itu dahulu
laba-laba anteng
merakit rumah
di bekas-bekas lamun jendela
kasur itu masih keras
dan lebarnya masih pas
untuk menelentangkan badan
dan mimpi-mimpi dulu
yang enteng dan sepele
coba tengok ke dinding
masa muda memang cocok
hanya dipigura/di pigura
supaya tak loncat
dimakan kebebasan
di luar jendela
beberapa hal bisa berpindah,
berpura-pura ada
atau hilang
yang bersetia hanya cermin
di mana dunia berbagi sama
/waktu dibuka, tak dikira/ sudah sesempit itu dahulu//. Dua larik awal tersebut bagi saya berfungsi sebagai keran pembuka luapan penggalan-penggalan kisah yang mungkin selama ini tak kita serap dalam-dalam.
Selama di perantauan sejak beberapa tahun terakhir, selain sibuk menekuni pekerjaan, saya juga kerap menekuni penghayatan kembali tentang arti rumah. Aktivitas santai seperti menyesap kopi sambil menyusun ulang tanggal-tanggal penting, atau perilaku sereceh merapikan momen-momen yang mustahil pergi dari ingatan, menciptakan sensasi manis-pahit yang tidak lagi terikat pada sebuah tempat atau suatu waktu.
Saya kira spirit lirisme dan kontemplatif macam itulah yang tersemat dalam puisi “rumah”. Pada bait kedua hingga keempatnya, tersusun jalinan linimasa yang runut dan rapi. Penggunaan benda-benda sebagai poros utama dalam adegan napak tilas dan refleksi tentang rumah, Willy tata dengan begitu apik. Imaji juga kuat terbangun melalui personifikasi benda-benda mati yang lekat dengan dimensi rumah.
/coba tengok ke dinding/ masa muda memang cocok/ hanya dipigura/di pigura//. Buyar dan tuntas sudah adegan melankolia menghirup kopi dan menguntai kenangan saya. Tiga larik pertama pada bait ketiga tersebut sukses mengguyur kesadaran bahwa segala yang sudah lalu tidak lain cukup bertempat di pijakan terakhir ia bersemat. Ada getaran personal dari rangkaian diksi /dinding/, /masa muda/, dan /dipigura/di pigura/. Saya seketika melihat ke sekeliling ruangan dan memandang pucatnya dinding, sepetak bentangan yang kerap terabaikan dan pemelihara suhu dingin yang baik. Di sana kah kelak seluruh kisah perjalanan saya akan membeku dan memutih?
Di tengah gempuran dunia maya di mana hidup seolah ditentukan oleh ‘tiga detik pertama’, batas kebenaran dan omong kosong yang semakin bias wujudnya, membaca puisi-puisi dalam antologi ini terasa seperti upaya untuk kembali menjadi manusia. Melambat dan menghayat. Mengakrabi diri kembali dan menerima. Perilaku kontemplatif dapat kita temukan sepanjang antologi dengan tema beragam.
Willy nampak telaten merawat momen-momen puitik dari pengalaman tubuh dan konflik batinnya. Lantas ia menaruh nyawa pada tubuh-tubuh gersang pengalaman sederhana – melalui puisi – yang selama ini kehilangan ruhnya. Ruh yang tercerabut oleh carut-marutnya negara, kekecewaan antar relasi sesama, pemaafan terhadap diri yang kian karib dengan kekacauan, dan lain sebagainya. Tentunya spirit demikian tidak hanya berupa kontemplasi liris pengiris hati atau penerimaan semata. Terlebih konsep penerimaan yang sebatas jatuh pada halusinasi optimistik yang mungkin sering kita idamkan dalam situasi penuh impitan. Sebaliknya, puisi-puisi Willy justru menawarkan bentuk lain dari penerimaan diri dalam jelmaan sinisme. Dimulai pada puisi “tempramen” (hlm. 7).
temperamen
bantinglah, banting
semua yang mulanya hening
keluar dan masukkan teriak
ke kebisuan kecoak-kecoak,
dinding, bantal, atau guling
sebagai tutorial
memakan diri sendiri
tidak pernah akan ada sapu
untuk membereskan kata-katamu
yang nonsens, tanpa sekuen
hanya keheningan
teman liat yang tahan
mendengar, memaafkan
rumah rahasia
yang tak bisa kau minta
di mana pernah
kau mengerti artinya
ada atau tak ada
Melalui puisi “tempramen”, saya kian sadar bahwa perilaku tantrum tidaklah mengenal usia dan agaknya sah-sah saja. Kontras dari puisi-puisi sebelumnya, “temperamen” dikemas dalam sinisme yang tajam. Amukan aku-lirik tegas tergambar dari bait pertama: membanting keheningan. Disusul bait berikutnya, kita diajak mendengar teriakan aku-lirik melalui saksi bisu dari serangkaian diksi /kecoak-kecoak, dinding, bantal, guling/. Rangkaian objek yang keberadaannya identik di dalam kamar pribadi tersebut, saya kira disimbolkan Willy sebagai pelampiasan sekaligus penonton setia dari diri yang kacau. Bait selanjutnya pun, sudahlah kacau tertimpa sial, /sapu/ pun rupanya tidak mampu membersihkan racauan di sekeliling telinga: /tidak pernah akan ada sapu/ /untuk membereskan kata-katamu/ /yang nonsens, tanpa sekuen//. Mungkin setelah akhirnya puas meledakan diri dan berbising ria di separuh puisi, layaknya fase perkabungan orang kebanyakan, pada bait keempat intensitas kemarahan mulai melandai. Kembali ke perilaku kontemplatif, dua bait terakhir menghadirkan suatu angan-angan tentang rumah. Sebuah ruang tenang dalam kepala aku-lirik di mana perihal ada dan ketiadaan pernah saling memahami.
Pasca adegan banting-membanting batin dalam puisi “tempramen”, semangat sinisme Willy masih berlanjut pada sajak berikutnya, “inkubasi” (hlm. 8).
inkubasi
awetkan
semua dendam
di kulkas
siapa tahu
kita bisa bikin hidup
yang dingin
tanpa urusan
juga tautan
tidur/tertidur
panjang, panjang
tanpa kejaran
di mana rumah
adalah semua hal
yang bukan
Serupa tapi tak sama, bila puisi “tempramen” sibuk menghardik kesunyian dengan berkobar-kobar, sinisme dalam “inkubasi” tersaji melalui nuansa batin yang lebih dingin. /awetkan/ /semua dendam/ /di kulkas/ /siapa tahu/ /kita bisa bikin hidup/ /yang dingin//. Pada larik-larik dua bait pertama tersebut, aku-lirik seolah mengeram kejengkelan pahit dengan ‘mengawetkan dendam dalam kulkas’. Dengan harapan, agar dendam beku tersebut dapat membuat hidup jadi lebih mudah dan mati rasa: /tanpa urusan/ /juga tautan/ /tidur/tertidur panjang/ /tanpa kejaran//. Lalu alih-alih larut dalam pendambaan akan rumah, kali ini Willy menutup puisi dengan memandang rumah sebagai negasi dan keterasingan dari bermacam ihwal.
Di samping warna-warni lirisme dan sinisme, variasi nuansa batin yang muram juga bisa ditemukan pada puisi-puisi lain seperti “hipokrit” (hlm. 10), “sabun” (hlm. 11), juga “alerta” (hlm. 21). Di sana Willy kembali menawarkan pemafhuman diri dalam sudut pandang getir, penerimaan sentimentil dari kegamangan hidup, hingga kekesalan dari hari-hari yang monoton.
Namun sejauh saya membaca, saya ingin memberi perhatian khusus kepada kehadiran sinisme dalam antologi ini. Dalam kebanyakan puisi-puisi yang ada, saya melihat bagaimana sinisme berfungsi sebagai topeng dari wujud batin yang kusut. Ada semacam usaha-usaha pengolahan konflik batin tertentu yang kemudian ditampilkan dalam rupa berbeda. Semisal dalam “tempramen”, bagaimana tempramental ditonjolkan sebagai bintang utama, namun di lapisan lain terdapat kesadaran tentang kepayahan memaafkan diri. Atau dalam “inkubasi”, di mana kekebalan atas segala perasaan membalut seisi puisi, tapi lantas tersirat kerapuhan dalam memaknai ruang bernama rumah. Paling tidak, sepenangkapan pendek saya sinisme di sini bekerja sebagai cara lain bersiasat. Baik dalam penyamaran sebuah pesan, atau pun sebagai tawaran lain dalam menikmati kekusutan pikiran.
Boleh saya katakan, seperti orang mati yang hidup ampuh menggenggam pikiran dan perasaan. Saya merasa dapat memperlakukan antologi ini layaknya rambu yang lihai menahan langkah yang sering hendak kabur dari memaknai peristiwa-peristiwa kecil. Walau sedikit, rasanya seperti ada perasaan ringan dari kehadiran puisi-puisi Willy sebagai kawan perjalanan. Hingga saya sampai pada puisi terpendek seantologi namun dengan efek gaung terpanjang, dari “reruntuhan” (hlm. 28). /wahai ludah di atas batu,/ aku perlu nasihatmu//. Astaga, duhai penyair, sudah sebegitu putus asanyakah kita pada lidah-lidah bijak di atas bumi ini lantas memerlukan nasihat seonggok ludah di atas batu?
Secara personal, saya menikmati kedekatan pengalaman batin yang intim antara ide-ide puisi Willy yang didominasi esensi menyoal kepulangan, juga aku-lirik yang sibuk mencari dan berangan-angan. Episode-episode sarat ketegangan dan sinisme juga meramaikan khasanah antologi sekaligus menampilkan kecakapan Willy Fahmy Agiska dalam mengolah nuansa kebatinan puisi dengan banyak ragam.
Usai menyelami 31 puisi dalam antologi ini, saya tidak hendak bermegah-megah dalam menyimpulkan seperti orang mati yang hidup. Karena sejatinya, buku ini semacam sebuah simpul pengikat tubuh-tubuh nihil ruh yang siap rubuh bila seutas saja diurai. Tema-tema puisi yang sebetulnya sudah ada dalam laku keseharian kita, jika saja kita mau berhenti sejenak kemudian memaknai, akan seketika terasa begitu dekat. Hal itu meyakinkan saya bahwa kita, manusia yang kebetulan memiliki pikiran dan perasaan, sudah semestinya akrab dengan penghayatan terhadap apa saja yang melintas dalam kehidupan. Bila versi amanat kata-kata mutiara: supaya tidak menyesal-menyesal amat.
Akhir kata, sungguh sebuah semesta puisi yang memantik perenungan khusyuk di tengah waktu yang kerap diburu-buru. Sekaligus medium empuk sebagai alasan menambah waktu melamun.
Agustus 2025. Al Medina.
Judul: seperti orang mati yang hidup
Kategori: Puisi
Penulis: willy fahmy agiska
Penerbit: Velodrom
Tahun Terbit: Mei, 2025
Jumlah Halaman: x + 36 halaman
QRCBN: 62-3927-9199-691