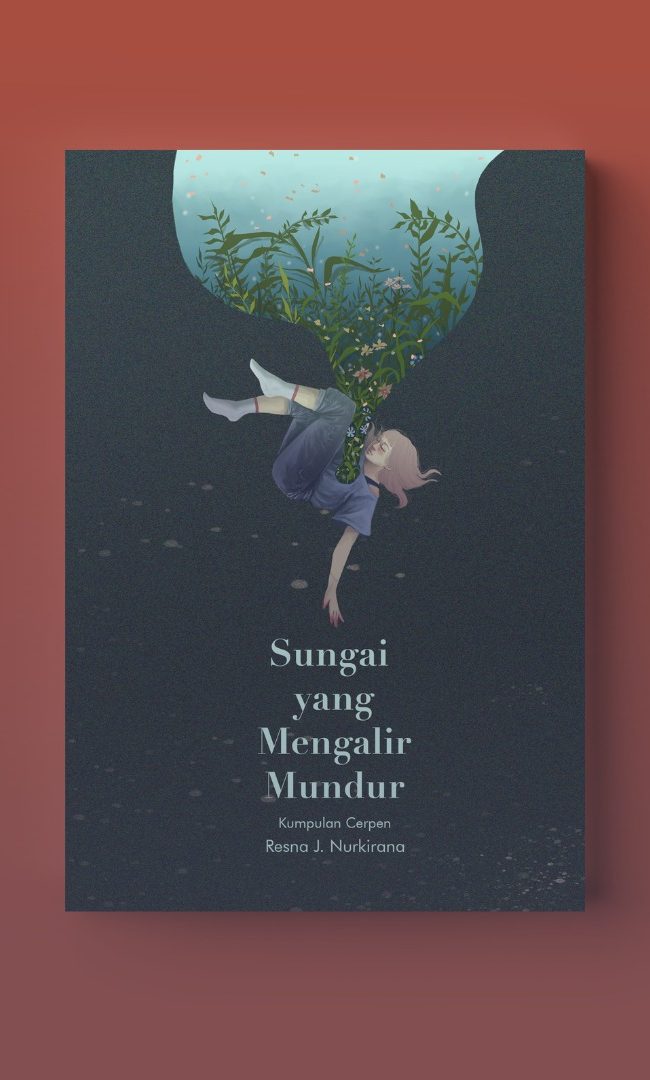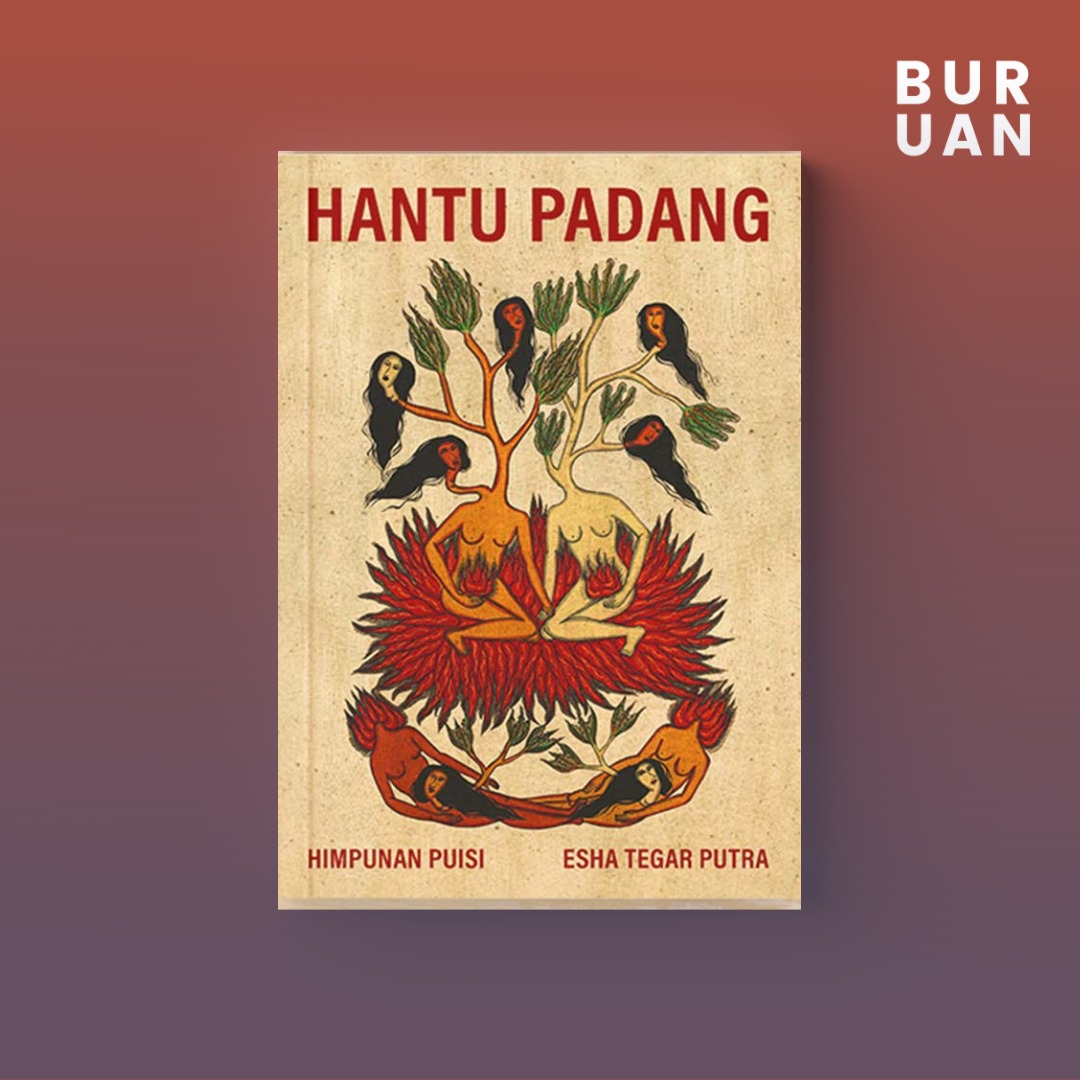
Hantu Waktu
Esai ini didiskusikan dalam gelaran Bukan Jumaahan Akbar di Perpustakaan Ajip Rosidi, Bandung, 11 Oktober 2025.
#1
Lauik sati, rantau batuah
(Laut sakti, rantau bertuah)
Peribahasa Minang itu menyaran pada pengertian rantau sebagai ruang yang liyan—bahasa, adat budaya, norma, sampai makanan. Tapi di situ pula letak tuahnya manakala seorang perantau bisa hidup menyesuaikan diri. Beradaptasi dan bernegosiasi dengan yang liyan, merawat harmoni sebagaimana ia adalah yang liyan juga. Pendeknya, rantau adalah ruang dialektis yang tuahnya adalah keluasan pengalaman seraya menginsafi makna identitas di tengah sekalian yang liyan.
Tapi sesekali semua jadi tak mudah juga. Bukan yang liyan benar yang jadi sebab, namun tegangan dari waktu dan ingatan. Dua entitas yang, kita tahu—apalagi bila meminjam pikiran Heidegger tentang Sein und Zeit—tidak selalu bergerak linear. Mengangkut semua yang silam ke dalam berbagai momen kekinian, membentuk pengalaman subjektif dan kesadaran akan keberadaan.
Dalam situasi demikian, rantau kemudian jadi sejenis hantu yang sibuk bernegosiasi di antara bayangan silam dan hasrat yang serba mustahil ihwal kini masa depan. Pulang pergi yang serba nostalgik, melankolis, dan penuh ratap. Situasi psikis yang jauh lebih rumit ketimbang lagu Kampuang nan Jauh di Mato .
Tetapi bukan berarti rantau tak lagi bertuah. Bahkan situasi itu pun sesungguhnya menjelaskan bagaimana ampuh dan bertuahnya rantau. Sekurang-kurangnya, begitu tuah yang diberlakukan pada Esha Tegar Putra manakala ia mengekalkan tegangan kesilaman dalam waktu dan ingatan sebagai hantu. Hantu yang menjadi peristiwa bahasa dalam kumpulan puisi “Hantu Padang”. Ketika kumpulan itu memenangi Kusala Sastra Khatulistiwa 2025, sesungguhnya Esha sedang melihat bagaimana tuah rantau itu bekerja.
#2
Berisi 39 puisi, “Hantu Padang” tak berjudul kecuali nomor urut, 0 sampai 38. Masing nomor tampak ingin berkesan sebagai puisi yang berdiri sendiri. Namun, dari hubungan keseluruhan tematik dan gaya pengucapan, kumpulan ini lebih berkesan berisi sebuah puisi panjang, dan penomoran difungsikan sebagai jeda. Bahwa jumlah bilangan sengaja disesuaikan dengan usia penyair saat manuskrip ini dirampungkan, tentu jadi kecurigaan yang sulit disangkal.
Kendati begitu, kecurigaan tersebut bukan jadi alasan memosisikan kehadiran Aku Subjek dalam buku ini adalah Aku Biografis, si penyair itu sendiri. Meski tulisan Esha di bagian awal seakan jadi pembenaran—juga penyebutan kedua anaknya dalam sajak. Dalih niscayanya hubungan puisi dan pengalaman personal penyair, bukanlah artinya menyangkal kodrat puisi sebagai peristiwa bahasa yang menyimpan banyak kemungkinan dalam pemaknaannya.
Sejak puisi “0”, Esha telah memberi gelagat pada strategi estetisnya dalam kumpulan ini.
Gelagat kebentukan yang rada-rada melain, setidaknya dari kumpulan sebelumnya, “Setelah Gelanggang Itu”. Meski secara tematiknya kecenderungannya masih menyisakan “Setelah Gelanggang itu”, namun strategi pendekatannya agak berbeda. Lebih dari sekadar keperluan menegaskan kepaduan isi dan bentuk, pendekatan itu tampaknya diperlukan sehingga eksplorasi bentuk bisa menjangkau pemaknaan yang lebih lapang. Termasuk melalui sejumlah penanda referensial yang diambil dari khazanah dendang saluang klasik atau pop Minang.
#3
“Hantu Padang” berperkara dengan masa lalu yang tak pernah berdiam di belakang,
ketika rantau kadung dianggap sebagai masa depan. Hantu ingatan yang gentanyangan saat perantau kembali pulang ke kota muasal. Kota yang maknanya lebih biografis ketimbang geografis.
Dalam kumpulan ini, beberapa puisi melukiskannya dalam bangun puitik dimana Aku bukan lagi subjek kehadiran, melainkan yang Aku yang “dihadirkan”. Semacam ekstase ingatan yang nostalgik. Aku adalah pengalaman keberadaan yang seakan mengalami penampakan yang silam lewat metafora dan imajinasi mengejutkan. Mulai dari bau hangus tempurung lutut kuda, patahan lambung kapal, dengung mantra dari kuburan lama, bangunan runtuh bekas pembantaian sapi, bau tuak hampir basi, serbuk garam dan percik kulit asam, akardeon yang dimainkan dari balik tumpukan bagan garam, sampai usus sapi yang bengkak. Semua adalah hantu yang menyaran jadi tempat dan peristiwa, terhubung kuat dengan narasi-narasi personal-primordial—hasrat masa muda, perantauan, pernikahan dalam suasana melakolia.
Esha membuat hantu-hantu itu dari upaya mengefektifkan elemen-elemen puitiknya. Perangkat pengucapan berasal dari sesuatu yang begitu dekat, mempersonifikasikan ruang psikis, mulai dari organ tubuh, belakang pintu, benda-benda keseharian, sampai masakan. Juga ketika bahasa menyodorkan lanskap peristiwa visual yang imajis; hantu-hantu bergelantungan di tiang lampu lama, tikungan dua jalan yang dihubungkan limpa berwarna biru, atau genangan air yang dijatuhkan sehelai rambut, atau kenangan yang diperbandingkan dengan santan masa yang didiamkan.
#4
Pada siasat yang lain, hantu ingatan yang primordial ditegaskan melalui kehadiran penanda-penanda referensial. Dendang Pariaman Lamo, Dendang Muara Labuh, Gamad Mati Dibunuh Talang Siligi, atau Tiar Ramon—penyanyi pop Minang terkenal. Selain hendak difungsikan sebagai referensi pemaknaan, Esha melakukan pemiuhan seperti yang dilakukannya pada bagian lirik Dendang Pariaman Lamo. Siasat untuk membangun relasi puitik. Begitu pula interpretasi tematiknya atas Dendang Muara Labuh.
Dendang saluang Minangkabau dan khazanah lagu pop Minang, tampaknya sudah menjadi menjadi modus penciptaan atau semacam “epistemogi estetika” Esha. Bukan hanya yang berihwal pada estetika suasana, tapi juga dari bagaimana ia mengolah rima. Dalam tegangan waktu dan ingatan yang mendominasi kumpulan ini, semua begitu terhubung—
kerinduan pada masa lalu yang hilang dan menjauh, ratap kecemasan pada masa depan. Lebih sekadar semacam kolase, penanda dendang salung Minang jadi bagian yang menyaran pada ide pemaknaan, seperti pada pada puisi “7.1”
Penyebutan Tiar Ramon jadi menarik. Lebih menarik lagi cara penyapaannya yang akrab, “Tiar”, yang muncul sejak puisi “1”. Tiar seolah seolah jadi super ego, personifikasi yang bisa menengahi kecemasan waktu dan ingatan—sebelum rantau menghabisi hasratku (“5”). Tiar juga yang diseru dalam puisi “24” sebagai harapan dan sandaran dari segala ratap ketakutan lenyapnya masa lalu oleh rantau.
#4
Jauh sebelum Esha menulis baris Aku harus kembali tiap aku pergi (Puisi “1”), Sitor Situmorang menutup puisinya “Upacara Sulang Bao di Lereng Pusuk Buhit”; Aku besok pulang/tapi seperti tak pernah pergi. Kedua penyair sedang memperkarakan hal yang sama, yaitu kota atau kampung muasal namun menyaran pada pendekatan tematik yang berbeda.
Meski banyak menghamparkan keindahan Danau Toba—bahkan ia dimakamkan di situ—puisi Sitor membayangkan suatu jarak. Kepulangan sebagai perantau tetaplah sebagai subjek kehadiran seperti terbaca dalam “Si Anak Hilang”. Begitu pula perjumpaannya dengan jejak yang silam dalam sajak “Balige” atau “Hutan Lintong”. Alih-alih jadi hantu, Sitor lebih mengungkapkannya dalam deskripsi yang datar, dan sebaliknya rantau adalah keriangan.
Sitor bisa jadi cara kita menatap tegangan waktu dan ingatan dalam “Hantu Padang” Esha. Hantu yang membuat pengalaman keberadaan mengalami tegangan di antara masa lalu dan masa depan. Jika dalam sajak Sitor kepulangan dan kepergian ke masa lalu—
Kampung muasal yang personal-primordial—berjarak secara tegas atau setidaknya kewajiban belaka; pada puisi Esha kepulangan itu tak cukup sekadar keharusan, melainkan juga hasrat.
Puisi-puisi Esha dalam “Hantu Padang” secara tematik memang terasa personal dan otobiografis. Namun, peristiwa personal sebagai modus penciptaan adalah suatu keniscayaan. Kodrat bahasa sebagai peristiwa penciptaan (puisi) menyimpan banyak kemungkinan ketika pengalaman personal itu jadi pengalaman bersama di hadapan waktu dan ingatan. Di hadapan dua entitas itu, sesungguhnyalah setiap orang mempunyai hantunya masing-masing.
Batujajar Regency, 11 Oktober 2025