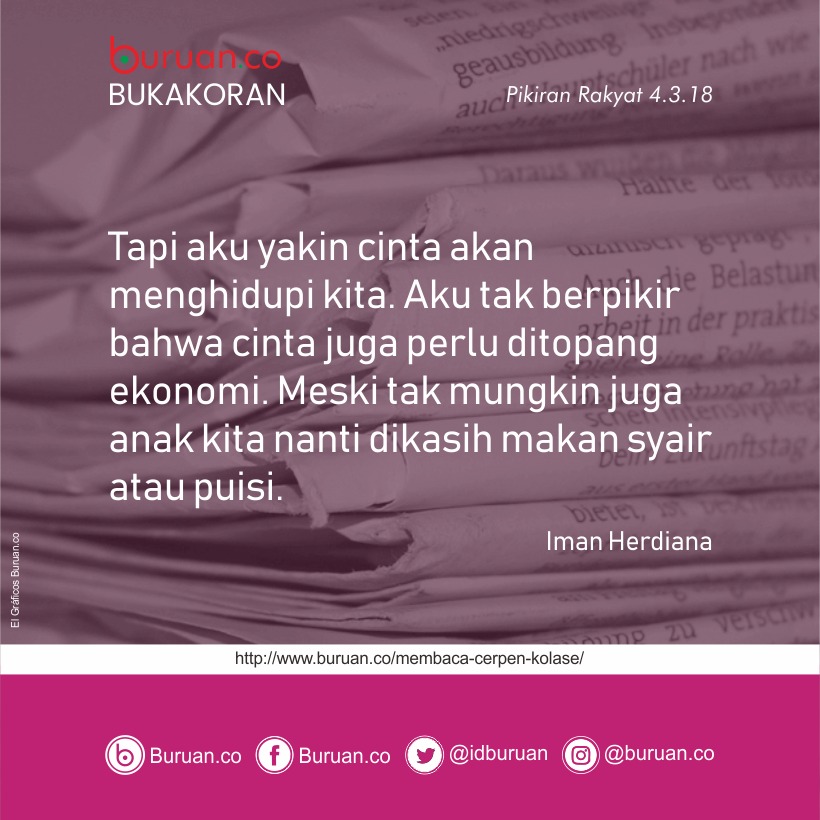Pahlawan Intan
Nama lengkapnya Intan Permatasari Hassan. Namun demikian, teman-teman seangkatan di program studi Manajemen Pemasaran Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia kadang memanggilnya Ibu Wilo. Itu karena sosok kelahiran Sukoharjo, 30 Maret 1989 ini, dianggap mirip dengan Ibu Wilodati, dosen PKN di prodi kami.
Di mata saya, Intan adalah teman yang tak banyak cakap. Pembawaannya kalem, hidupnya lempang. Tipikal mahasiswa normatif yang urusannya di kampus tak lebih dari kuliah dan kuliah.
Pada 2015, ketika saya dan belasan teman seangkatan masih bertungkuslumus menyelesaikan skripsi, Intan sudah lulus. Lewat Instagram, kami tahu bahwa ia sudah menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang lucu: Ishaq. Saya senang melihat teman-teman perempuan menjalani kehidupan baru sebagai ibu. Di pertengahan usia 20-an, bagi sebagian orang, hal semacam itu adalah puzzle yang menyempurnakan indahnya kehidupan.
Hubungan pertemanan yang terbatas dengan Intan membuat saya tak tahu banyak soal dirinya, soal kegembiraan dan kesedihannya. Satu-satunya kesan saya: nyaris tak ada hal menonjol dari pribadinya. Namun justru karena itulah rasa hormat dan ketakjuban demi ketakjuban muncul manakala setahun belakangan, lewat sebuah pesan di Whatsapp, kami tahu bahwa perempuan ramah berkacamata itu adalah perempuan luar biasa. Ia mengidap kanker payudara stadium 2B, namun tak ada keluhan atau upaya menarik simpati di akun media sosialnya.
Rabu malam (4/9/2019), di grup Whatsapp MPP 2008 Happy Family, sebuah pesan yang tak biasa kami terima.
“Assalamualaikum temen2 semua, ini suaminya Intan, saat ini Intan sedang kritis. Saya memohon doa dari temen2 semoga mendapatkan kekuatan mengahadapi masa kritisnya. Terima kasih banyak doa dan dukungan temen2. Jazakallah Khairan Kasira.”
Sementara doa dan dukungan masih terus disampaikan, sekira satu setengah jam kemudian nomor Intan kembali mengirim pesan. “Innalillahi wa inna ilaihi raajiuun…”
Nasib, kata Chairil Anwar, adalah kesunyian masing-masing. Saat Rianne Rahayu, teman yang beberapa waktu belakangan cukup intens menjalin komunikasi dengan Intan mengirimi foto tulisan almarhumah di antologi Cancer, Jangan Bunuh Aku!, saya tahu: nasib Ibu Wilo kami adalah bentangan kesunyian yang melelahkan.
Ishaq bahkan baru saja melewati ulang tahunnya yang kedua. Sedangkan Aidan masih menyusu padaku. Setiap melihat wajah kedua anak itu, rasa takut kembali memuncak. Tak kuasa rasanya menatap wajah polos para jagoanku.
Bulan berganti, tidak terasa jadwal operasi semakin mendekati harinya. Memasrahkan pada takdir Allah, semoga ini jalan kesembuhan terbaik. Hingga waktu itu, tepat sebulan sebelum operasi, kurasakan perubahan terjadi pada tubuh. Kurasakan mual di pagi hari, keinginan makan tertentu, dan menstruasi yang tak kunjung tiba. Kucoba menggunakan testpack untuk menjawab rasa penasaran. Dua garis yang kutakutkan muncul, badanku limbung. (hal. 68)
Intan divonis menderita kanker saat ia masih menyusui anak keduanya kala itu, sang bayi kerap menangis dan menolak disusui dari payudara sebelah kiri.
Aidan sudah memberikan sinyal yang tak mampu kutangkap, jadi Aidan hanya menyusu dari sebelah kanan saja. Itupun harus ditambah susu formula karena ASI-ku kurang mencukupi. (Hal. 66).
Saran dokter agar dilakukan operasi—yang dijadwalkan 6 bulan setelah Intan divonis kanker—akhirnya mesti ditangguhkan lagi mengingat dalam kondisi hamil masuk ruang bedah sangat berisiko. Tragisnya, di saat bersamaan, hormon kehamilan justru membuat sel kanker makin ganas. Dalam kondisi semacam inilah kesunyian nasib menghamparkan kertas ujian yang jawabannya sukar dijabarkan.
Tak ada cara lain, aku harus menjalani kemoterapi saat hamil untuk menekan pertumbuhan sel kanker. Pilihan yang sulit. Karena, sedikit banyak akan berpengaruh pada perkembangan janin. (Hal. 68).
Beberapa waktu lalu, saat merasa ada di titik nadir kehidupan, dalam nada sungguh-sungguh—lazimnya semua nasihat orangtua—ibu saya mengingatkan: “Jangan pernah merasa sendiri. Jika kamu dirundung cobaan, mama akan selalu ada, bahkan jika harus bertaruh nyawa.”
Saya tergetar dengan ungkapan itu, dan kian tergetar saat mendapati contoh konkretnya pada diri Intan.
Inilah medan perangku, apakah aku akan menang melawannya atau mati dengan rasa bangga di dada karena telah berjuang hingga akhir. (Hal. 72).
Dalam “Cinta Sejati”, penyair favorit saya Wislawa Szymborska menyatakan bahwa cinta yang sulit dijelaskan itu sebaiknya dirayakan dalam senyap—sebagaimana seseorang melewati kesulitan hidupnya yang terberat. Namun di era serba terbuka begini, keduanya tampak sulit dilakukan. Media sosial adalah candu yang membuat penggunanya untuk senantiasa mengabarkan segala sesuatu kepada dunia.
Dalam diri Intan, lazimnya dalam diri setiap ibu, kemampuan menyembunyikan kesedihan itu ada—dan itulah yang membuat kesan dirinya yang biasa-biasa saja jadi terlihat kuat dan penuh pesona. Saat terakhir kali bertemu pada bulan Ramadan setahun lalu, Intan tak sedikit pun menunjukkan pergulatannya dengan nasib kepada kami teman-temannya.
Mengeluh pun malu, karena tersadar lebih banyak rasa cinta yang Allah berikan. (hal. 72).
Ajaran agama yang saya yakini menyebut bahwa “termasuk dari simpanan-simpanan kebaikan adalah menyembunyikan musibah-musibah, sesakitan, serta sedekah.” (H.R. Abu Nu’aim, dishahihkan oleh Al Hafidz Imam As Suyuthi).
Saya percaya Intan telah sungguh-sungguh mengamalkan ajaran itu. Karenanya, saya merasa kerdil mengingat hal-hal yang timbul lantaran kenaifan sendiri kerap membuat saya mengeluh dan mengeluh—di tengah keleluasaan saya selama ini.
“Hidup,” kata Rendra, “tidaklah untuk mengeluh dan mengaduh/Hidup adalah untuk mengolah hidup. Intan, penyintas kanker yang tangguh itu, kini telah memasuki rahasia langit sehabis mencipta dan mengukir dunia.
Ungkapan mengukir dunia tak jarang diasosiasikan dengan hal-hal monumental. Karena itu, saya lebih sering merasa hambar tiap kali mendengar cerita berulang mengenai sosok-sosok besar yang sanggup mengubah keadaan.
Tokoh-tokoh inspiratif seperti Bunda Theresa maupun Hellen Keller, misalnya, tiba-tiba hadir serupa fantasi lantaran sulit menemukan irisan langsungnya dengan kehidupan saya sehari-hari. Demikian juga upaya-upaya besar seperti mengingatkan bahaya pemanasan global yang dilakukan Greta Thunberg di Swedia atau keberhasilan Muhammad Yunus mengikis lintah darat di India. Keduanya terkesan serupa dongeng pengantar tidur yang melenakan, tapi tak kuasa menggerakkan apa pun dalam diri saya.
Sementara Intan, juga sosok-sosok yang tanpa diminta tiba-tiba mengulurkan tangannya saat saya membutuhkan pegangan, justru membuktikan bahwa kebaikan dan heroisme, kasih sayang dan ketulusan, inspirasi dan hal-hal yang menggugah kesadaran, sebetulnya berserakan di sekitar.
“Betapa banyak hal tergenggam dalam tangan mereka yang kosong,” kata Szymborska, dalam sajaknya yang lain, “Ucapan Terima Kasih.” Pernyataan itu relevan dan akan terus relevan untuk sosok-sosok seperti Intan.
Setelah kepergiannya, sejumlah teman menyebut ibu tiga anak ini (selain Ishaq dan Raidan, Intan juga meninggalkan si kecil Ariella yang tak bisa mencicipi air susunya) sebagai seorang teladan dalam kehidupan mereka. Di titik ini saya percaya, siapa pun memiliki—sekaligus bisa menjadi—teladan cum pahlawan bagi orang-orang di sekelilingnya. Tak jarang, dengan caranya masing-masing, orang-orang yang sering kali tak disangka-sangka ini justru merupakan sosok-sosok paling siap yang berjaga dalam kesunyian nasib kita.
Dan, lebih dari sekadar keberanian, yang menarik (bahkan sering kali mengharukan) dari hadirnya seorang pahlawan adalah kemunculannya yang tak terduga, bukan?